Berpikir Dan Menjadi Kaya Pdf Merger
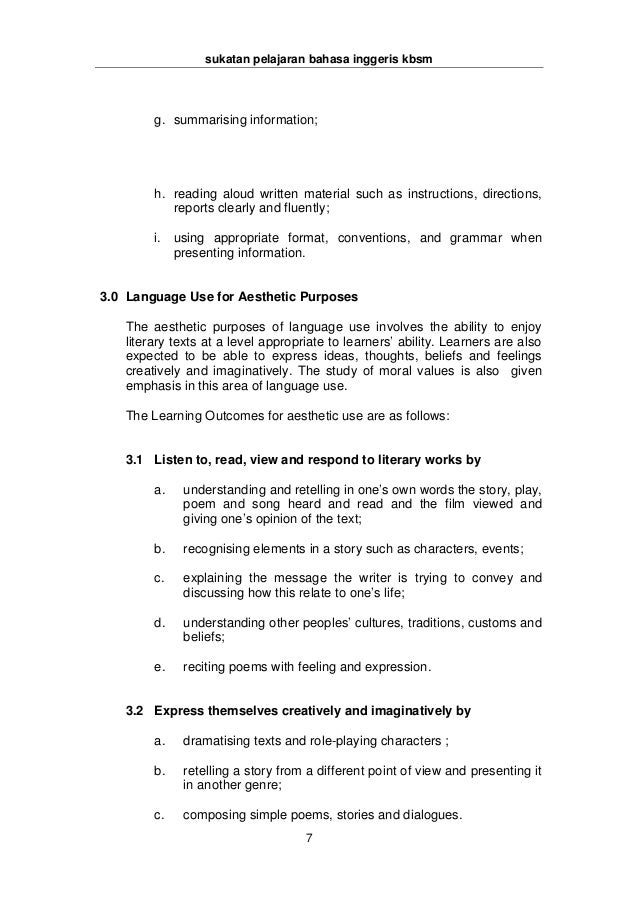
Pada 2012, saya masih ingat, pernah berdiskusi dengan seorang kawan yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya tentang Rohingya. Saya tanya, “Terus, gimana-gimana soal Rohingya?” “Kompleks cuk, gue masih bingung di kesimpulan” kata dia. “Orang-orang Rohingya ini ditolak di Myanmar karena dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh, mereka ini orang-orang ‘Bengal’ kalo menurut pemerintah Myanmar.
Secara legal, mereka juga nggak diakui punya kewarganegaraan Myanmar” tambah dia Saya tanya lagi ke kawan ini, “Lah, pindah aja ke Bangladesh” Dia menjawab “Orang-orang Rohingnya juga ditolak di Bangladesh. Soalnya Bangladesh menganggap mereka sebagai orang Myanmar. Ini, ditolak dimana-mana, mereka ini stateless” Saya tertawa. Kemudian dia balik bertanya “Kalo menurut lo?” Saya jawab “Kalo jangka panjang, Myanmar harus mengakui si Rohingya-Rohingya ini. Kalo jangka pendek, Bangladesh dan negara-negara tetangga lain yang berdekatan dengan Myanmar harus menjadi Buffer Zone untuk si pengungsi-pengungsi Rohingya.
Tapi nggak usah terima semua maksud gue” Kata dia “Susah cuk, mereka ini kan tidak dianggap di negaranya sendiri dan ancaman keamanan untuk negara-negara lain” Saya jawab lagi “Lah, gue ngomong soal kemanusiaan dan keamanan Di (nama kawan saya ini Dian). Lo tolak ini orang-orang, lama-lama jadi teroris mereka, lama-lama jadi ancaman keamanan baru untuk negara-negara yang tadi menolak” Lima tahun setelah diskusi ini, di tengah-tengah kondisi lingkungan strategis dimana: Kekuatan ISIS perlahahan-lahan melemah.
Kemudian muncul suatu ‘Daulah Islamiyah’ di Filipina Selatan. Di Rakhine State, Myanmar muncul satu kelompok ‘pemberontak’ baru yaitu Tentara Penyelamatan Arakan-Rohingya (Arakan-Rohingya Salvation Army) (ARSA) yang menganut ekstrimisme islam. Kalo soal kebenaran prediksi saya, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Pola yang sama terjadi dalam sejarah, dimana-mana. Menyerang Dahulu, Ribut Kemudian Para pembaca mungkin sempat melihat gambar-gambar hoax yang viral di media sosial tentang kondisi orang-orang Rohingya. Para pembaca juga mungkin sempat membaca berita-berita heboh tentang mereka (orang-orang Rohingya) yang diperkosa, disiksa dan dibunuh dengan metode-metode yang jauh dari pri-kemanusiaan. Ternyata hal-hal ini tidak sepenuhnya benar.
Memang benar bahwa terdapat ratusan (sekitar 400) orang Rohingya yang tewas. Benar juga bahwa terjadi eksodus puluhan ribu manusia dari Myanmar ke Bangladesh. Akan tetapi tidak banyak yang tahu, hal ini terjadi karena ARSA menyerang terlebih dahulu. Pada bulan Agustus tahun ini, ARSA tercatat melakukan serangan yang terkoordinasi ke 30 pos polisi dan markas tentara di Rakhine State. Serangan ini direspon balik oleh militer Myanmar dengan melakukan ‘operasi militer’ untuk ‘menumpas teroris’ di Rakhine State. Bahwa korban ‘operasi militer’ ini lebih banyak masyarakat sipil karena milisi-milisi ARSA menjadikan mereka (sipil) sebagai tempat perlindungan.
Kondisi saat ini kurang lebih sama dengan yang terjadi pada 2012. Tidak jauh berbeda. Bedanya, yang sekarang dipicu serangan ARSA. Dulu, sekitar Bulan Mei-Juni 2012, seorang wanita Rakhine (salah satu etnis di Myanmar) diperkosa oleh tiga orang Rohingya. Tidak lama konflik terjadi antara etnis Rohingya dengan etnis-etnis lain di Myanmar yang dibantu kelompok tentara. Dampaknya gelombang pengungsi dari Myanmar ke Bangladesh dan negara-negara ASEAN yang lain, termasuk ke Indonesia (di Aceh).
Berpikir Ala Orang Kaya Written by Ongky Hojanto Friday. Siapa yang tak ingin menjadi kaya. Bergelimang harta dan hidup penuh kemewahan, bahkan. Komunikasi Interpersonal: Definisi, Klasifikasi, Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi Interpersonal, Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen.
Saya perlu menekankan kepada para pembaca. Saat itu (2015) tidak semua negara mau menerima pengungsi Rohingya. Malaysia misalnya, mengusir mereka di laut lepas. Menteri Dalam Negeri Malaysia menjelaskan hal ini “Kami sudah terlalu baik dengan orang-orang yang masuk dengan ilegal ke perbatasan Kami. Kami juga mencoba memperlakukan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Tetapi Kami tidak bisa menerima ‘banjir’ seperti ini. Atau Thailand, yang juga mengusir mereka saat berada di laut lepas dan daratan.
Hal ini lebih dapat dipahami, mengingat Thailand mempunyai pengalaman buruk ketika menangani pengungsi konflik Kamboja beberapa dekade lalu. Selain itu, Thailand juga ‘trauma’ dengan pengungsi-pengungsi muslim, mengingat mereka cukup kewalahan dengan pemberontakan ‘ekstrimis islam’ di Thailand Selatan. Hanya Indonesia yang mau menerima mereka dengan ‘tangan terbuka’ pada awalnya, akan tetapi dalam waktu yang tidak lama. Sekitar bulan Oktober 2015 –atau dua tiga bulan setelah diterima di Aceh, beberapa pengungsi wanita Rohingya mengaku telah diperkosa oleh oknum-oknum masyarakat di Aceh. Ternyata hal ini sama sekali tidak benar.
Sayangnya berita ‘perkosaan’ terlanjur menyebar, masyarakat dunia kemudian menghujat Aceh dan Indonesia ‘ramai-ramai’ karena dianggap tidak mampu menangani mereka sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak lama setelah kasus perkosaan ini mencuat, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan bahwa TNI berusaha untuk mencegah lebih banyak dari mereka yang masuk ke wilayah Indonesia, karena berpotensi besar membuat konflik sosial. Ekstrimis Religi Kanan di Myanmar Saya pikir-pikir “Pantas saja ditolak di Malaysia dan Thailand. Belum lama diterima di Indonesia, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak lazim. Apalagi di Myanmar sana, kemungkinan besar perilaku mereka lebih tidak lazim lagi”.
Sembari bertanya perihal alasan orang-orang ‘asli’ di Myanmar menolak dan membenci mereka (orang-orang Rohingya). Bahwa penolakan dan kebencian terhadap etnis Rohingya sedang mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan kebelakang. Terdapat kebangkitan suatu ‘Nasionalisme Buddha’ di Myanmar.
Dimana kelompok-kelompok ‘nasionalis’ melakukan demonstrasi untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Bahkan sampai melakukan sweeping terhadap orang-orang Rohingya di beberapa wilayah urban di Yangoon. Quantum Of Solace Game Serial Key on this page. Salah satu kelompok ‘nasionalis’ yang paling populer adalah Ma Ba Tha yang dipimpin oleh Biksu Ashin Wirathu. Saya mengakui bahwa retorika-retorika Wirathu tergolong berbahaya. Salah satu alasannya karena Wirathu mengklaim identitas pemeluk Budha terganggu dengan eksistensi kelompok minoritas pemeluk agama Islam di Myanmar. Akan tetapi, setelah mencari tahu lebih mendalam, ternyata tempat tinggal Wirathu dibakar dan keluarganya dibunuh oleh milisi-milisi Rohingya (akar kelompok ARSA) beberapa tahun lalu.
Baru bulan lalu pacar saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Myanmar. Dia bercerita tentang ‘betapa kesalnya’ orang-orang Myanmar kepada ‘orang-orang Bengal ini’. Ternyata, sebagian besar perilaku kekerasan dan kasus kriminalitas di Yangoon –Ibukota Negara Myanmar dilakukan oleh mereka -orang-orang Bengal.
Apakah alasan ‘kesal’ mereka sesederhana dendam dan kondisi real di lapangan? Saya pikir tidak sederhana para pembaca.
Lebih jauh lagi, saya menduga kelompok militer yang masih berkuasa di ‘balik layar’ merupakan ‘dalang’ yang ‘bermain’ dalam kebangkitan Nasionalisme Buddha di Myanmar. Termasuk aktor utama yang melakukan ‘sekuritisasi’ dengan objek ancaman berupa orang-orang Rohingya, dan kemudian diterima oleh masyarakat sipil di Myanmar. Jika melihat catatan sejarah, para pembaca akan mengetahui bahwa asumsi saya beralasan. Junta militer merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap status ‘ stateless’ orang-orang Rohingya seperti saat ini. Seperti yang dikutip dari Benedict Rogers dalam Burma: A Nation at the Crossroads, bahwa rejim junta militer dibawah Jenderal Ne Win-lah yang bertanggung jawab terhadap keluarnya Undang-Undang Imigrasi Tahun 1974 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang tidak menuliskan etnis Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui di Myanmar.
Padahal pada rejim sebelum ini –yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya masih diakui di Myanmar. Dengan fakta-fakta ini, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan soal konflik Rohingya –sama seperti lima tahun lalu telah diskusikan dengan kawan saya. Pertama, menimbang pemerintah Myanmar merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap krisis Rohingya ini, baik ditinjau dari aspek politik –bahwa mereka berada di wilayah kekuasaan Myanmar, atau ditinjau dari aspek sejarah. Dengan kata lain, saya sepakat untuk ‘menekan’ Perdana Menteri Aung San Suu Kyi untuk mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang mempunyai kewarganegaraan Myanmar.
Hal ini merupakan resolusi konflik dalam jangka panjang. Kedua, menimbang letak Bangladesh sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan Myanmar, selain itu melihat kedekatan etnis ‘Bengali’ di Bangladesh dengan etnis ‘Rohingya’ ini. Akan lebih baik jika Bangladesh yang menjadi ‘Buffer Zone’ utama untuk menampung para pengungsi Rohingya. Sembari langkah-langkah politik diambil Perdana Menteri Aung San Suu Kyi. Adapun negara-negara yang merespon ‘keras’ kebijakan Myanmar –seperti Turki, Iran, Indonesia atau organisasi-organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Persatuan Bangsa-Bangsa dapat mengirimkan bantuan-bantuan internasional kepada pemerintah Bangladesh. Hal ini merupakan resolusi konflik dalam jangka pendek. Bantuan-bantuan internasional, terutama terkait ‘pendanaan’ memang dibutuhkan Bangladesh.
Seperti saya telah sebut di awal tulisan ini, Bangladesh sebenarnya menolak pengungsi-pengungsi Rohingya. Alasannya tidak lain karena Bangladesh merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Alasannya tidak bukan karena Bangladesh juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-8 di dunia –sebanyak 166 juta jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.200 orang per kilometer persegi. Dengan kata lain, kondisi mereka ‘terlalu berat’ untuk menerima dan mengurus ‘tambahan’ manusia lainnya. Ketiga, Perdana Menteri Aung San Suu Kyi hendaknya melakukan ‘desekuritisasi’ isu terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Langkah ini sangat penting untuk mereduksi penolakan dan kebencian etnis-etnis lain di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan strategi ‘desekuritisasi’ dalam tulisan ini, mungkin lain waktu.
Keempat, bahwa ketiga langkah di atas tergolong penting untuk menyelesaikan konflik Rohingya yang terjadi sejak lama dan berlarut-larut. Saya melihat potensi ancaman keamanan yang lain jika konflik Rohingya tidak segera diselesaikan, yaitu ketika Rakhine State –yang merupakan perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh di masa depan akan menjadi salah satu basis kelompok teroris besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Konflik Rohingya Sebagai Alasan Utama Eksistensi Kelompok Teroris Transnasional Saya rasa sangat logis untuk mengatakan bahwa Etnis Rohingya yang selama ini ‘terdzalimi’ atau ‘termarginalisasi’ sangat potensial untuk direkrut kelompok-kelompok ekstrimis islam seperti ISIS dan Al-Qaeda.
Asumsi ini kemungkinan besar benar adanya, terlebih dengan melihat perkembangan pemikiran ‘jihad’ di kalangan muda Rohingya dan peningkatan identitas kolektif (senasib seperjuangan) pada etnis Rohingya ketika mereka membandingkan kondisi mereka dengan kondisi etnis-etnis lain yang beragama Islam yang juga sedang ditekan pemerintah, seperti etnis Moro di Filipina atau orang-orang Pattani di Thailand. Pada 2014, ketika kelompok-kelompok ekstrimis islam di India Besar (India, Pakistan dan Bangladesh) mengumumkan pembentukan Al-Qaeda di Sub-Kontinen India (AQIS). Selain menargetkan pemerintah-pemerintah di negara masing-masing, mereka juga berniat menyelamatkan orang-orang Rohingya dari ketidakadilan dan tekanan oleh pemerintah Myanmar.
Misalnya pada Juni 2015, kelompok Tehreek-e-Taliban di Pakistan dikabarkan telah menawarkan bantuan berupa uang dan pelatihan kepada orang-orang di Rohingya. Atau pada April 2016, seperti tertulis dalam Majalah Dabiq ISIS, salah seorang milisi Bangladesh Abu Ibrahim berkeinginan untuk membantu umat muslim di Myanmar dengan segal cara. Terakhir pada 2017, seorang simpatisan ISIS ditangkap di Malaysia karena terbukti ingin berangkat ke Rakhine State, Myanmar.
Salah satu yang paling serius adalah eksistensi ARSA saat ini di Rakhine State. Walaupun ideologi kelompok ini tidak untuk mendirikan negara islam, seperti halnya ISIS atau Al-Qaeda, melainkan untuk membela dan menyelamatkan umat muslim Rohingya dari pemerintah Myanmar, beberapa pengungsi Rohingya menyebutkan bahwa islam yang dianut milisi-milisi ARSA tergolong ‘ekstrim’. Selain itu, ARSA terbukti telah menjalin hubungan dengan kelompok ekstrimis lain di Arab Saudi dan Pakistan untuk kepentingan penggalangan dana. Saya menganggap ARSA-lah yang paling bertanggung jawab terhadap eskalasi konflik yang makin tinggi di Myanmar bulan-bulan ini.
Hal ini tidak terlepas dari serangan yang dilakukan ARSA kepada puluhan polisi dan tentara di Rakhine State pada 25 Agustus 2017. Termasuk pembunuhan beberapa orang hindu di Rakhine State pada 27 Agustus 2017. Aksi ini kemudian direspon (sayangnya berlebihan) oleh masyarakat dan militer Myanmar. Lebih jauh lagi berdampak pada ‘pengungsian massal etnis Rohingya episode 2’ dalam dekade ini. Selain itu saya juga menganggap ARSA sebagai aktor dibalik gambar-gambar ‘Hoax’ yang tersebar di media sosial baru-baru ini. Hal ini tidak lain karena salah satu strategi kelompok ini adalah untuk mendapatkan perhatian dan dukungan internasional, terutama negara-negara muslim untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu tinggal di Rakhine secara permanen.
Akhir tulisan ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk pembaca. Bersimpati boleh, terlebih untuk saudara kita dalam kemanusiaan. Akan tetapi, jangan menjadi simpatisan yang buta.
Denny Indra Sukmawan Deputi Kajian Strategis Lingstra. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dan Merdeka! Para pembaca yang setia, pada tulisan kali ini saya coba membahas perihal penanaman modal asing.
Bagaimanapun juga diskursus tentang penanaman modal asing versus kemerdekaan masih belum selesai. Saking tidak selesai-selesai, jika para pembaca mencarinya di google, terdapat suatu pola dalam diskursus ini: Ramai dibicarakan netizen ketika isu renegosiasi Freeport atau isu ancaman Tiongkok mencuat ke publik. Ramai juga dibahas setiap bulan Agustus. Apakah kehadiran Freeport di Papua atau Chevron di Riau petanda kita benar sudah merdeka? Atau malah sebaliknya.
Apakah besarnya rasio penanaman modal asing dari Jepang, Tiongkok dan Korea petanda kita benar-benar sudah merdeka? Atau malah sebaliknya.
Apakah penyambutan ‘berlebihan’ kepada ‘orang-orang kaya’ dari Arab oleh karena pemerintah kita berharap pada ‘sesuatu hal’ petanda kita belum merdeka? Dalam kasus Freeport dan Chevron, saya berani bilang banyak pembaca yang menjawab Indonesia ‘belum merdeka’. Sedangkan dalam kasus Jepang dan Tiongkok, saya berani bilang lebih banyak pembaca yang menjawab Indonesia ‘sudah merdeka’. Jawaban macam ini bisa muncul karena indikator ‘kemerdekaan’ kita lebih pada upaya-upaya menghilangkan eksistensi Freeport dan Chevron dari tanah air Indonesia.
Terlalu fokus dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kita sampai lupa dengan perusahaan-perusahaan dari kawasan Asia Timur. Apalagi berupaya mencari solusi terkait ketergantungan kita terhadap produk-produk Honda dan Samsung, termasuk dengan pasar online ala Alibaba. Untuk kasus ketiga, silakan para pembaca pikir-pikir sendiri. Jika diskursus ‘penanaman modal asing versus kemerdekaan’ sudah banyak yang membahas. Bagaimana dengan diskursus antara ‘penanaman modal asing versus keamanan nasional’.
Saya sendiri telah mencarinya di google dan terbukti belum banyak orang yang membahas secara lebih mendalam. Padahal diskursus yang kedua ini terlihat lebih menarik, terlebih jika para pembaca berkenan untuk mencari kembali di google perihal kutipan-kutipan berita media online yang saya tulis di bawah ini: “ Presiden Joko Widodo menginginkan rakyat mengetahui betul manfaat sebuah investasi, baik investasi dari negara luar atau dalam negeri. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin pihak kementerian hingga pemerintah setempat aktif menjelaskan tentang imbas positif sebuah investasi asing kepada masyarakat Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan melibatkan Panglima TNI, Kepala Polri, hingga Kepala BIN dalam hal masuknya investasi di Indonesia. Menurut Jokowi, ini semata-mata demi kelancaran investasi itu sendiri Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia.
Stabilitas dalam negeri adalah faktor penting bagi investasi. Sebab kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi saat ini sedang tinggi-tingginya” (Untuk Tepis Hoaks soal Investasi Asing, Ini Permintaan Khusus Jokowi. LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM STRATEGI SATU SABUK, SATU JALUR: PERSPEKTIF OFENSIF REALIS Oleh Denny Indra Sukmawan ABSTRAK Kata Kunci: Kerjasama Militer, Amerika Serikat, Ancaman Militer, Satu Sabuk Satu Jalur, Jalur Sutera Maritim, Republik Rakyat Tiongkok, Geopolitik dan Geostrategi, Laut Tiongkok Selatan, Realisme Ofensif, Dilema Keamanan. ABSTRACT Keyword: Military Cooperation, United States of America, Military Threat, One Belt One Road, Maritime Silk Road, People’s Republic of China, Geopolitics and Geostrategy, South China Sea, Offensive Realism, Security Dilemma. Pembuka Istilah ‘Satu Sabuk, Satu Jalur/SSSJ’ ( One Belt, One Road) pertama kali disebutkan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping pada September 2013 di Kazakhstan. Dalam pidato di Universitas Nazarbayev, Xi berbicara tentang kebangkitan rute perdagangan bersejarah ‘Jalur Sutera/JS’ ( Silk Road) di Asia Tengah.
Saat itu pernyataan Xi tidak terlalu ditanggapi oleh media internasional. Sampai pada Oktober 2013, Xi mengunjungi Indonesia dan berbicara di depan parlemen Indonesia tentang kebutuhan untuk membangun ‘Jalur Sutera Maritim Abad ke-21/JSM’ ( Maritime Silk Road). Pemerintah RRT membutuhkan waktu dua tahun untuk memformulasikan gagasan Xi dalam suatu strategi. Terhitung pada Maret 2015, gagasan SSSJ diadopsi dengan sejumah tujuan prioritas dan prinsip-prinsip oleh Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi ( National Development and Reform Commission). Sejak saat itu, SSSJ secara formal menjadi bagian utama strategi ekonomi internasional dan politik luar negeri RRT. ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi RRT dalam tiga dekade terakhir. Pada dekade pertama (1980-1990) RRT melakukan reformasi ekonomi dengan membuka arus investasi asing ke dalam negeri ( Economic Reformation).
Satu dekade kemudian (1990-2010), RRT terfokus pada upaya-upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kerangka ‘Kebangkitan yang Damai’ ( Peaceful Rise/Peaceful Development). Hasilnya terbilang impresif, salah satu indikatornya, dalam dua dekade ini, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) RRT selalu diatas 10%.
Adapun sekarang RRT disebut sedang melakukan ‘ekspansi pengaruh’ ( expanding its influence) ke luar negeri dalam kerangka SSSJ. Strategi ini -seperti yang dicatat sejarah, termasuk strategi yang baik ( good strategy), karena mampu diimplementasikan melalui turunan-turunan kebijakan ekonomi, politik dan militer yang sinergis. Dalam SSSJ, kebijakan ekonomi dapat dilihat dari langkah RRT membentuk Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (BIIA) pada 2014.
Sebagai inisiator, RRT berkontribusi sebesar 50 miliar dollar untuk modal BIIA atau setengah dari total modal. Kedepannya BIIA akan menjadi ‘tulang punggung’ bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di beberapa negara mitra.
Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antar kawasan. Konektivitas yang dimaksud akan dicapai melalui pembangunan ‘rute darat’ dari RRT melewati Asia Tengah dan Asia Selatan, berlanjut ke Timur Tengah dan Eropa. Serta melalui ‘rute laut’, dari RRT melewati perairan-perairan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa.
Sinergi antara kebijakan ekonomi dan politik dapat dilihat dari diplomasi aktif Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan RRT. Selama 2015 saja, kedua instansi telah mengunjungi lebih dari dua puluh negara, belum termasuk partisipasi dalam beberapa forum bilateral dan multilateral untuk mempromosikan SSSJ dan mengajak negara-negara lain bergabung kedalam BIIA. Sinergi juga dapat dilihat pada implementasi kebijakan militer RRT yang disebut beberapa pihak menjadi lebih asertif di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Pendapat ini tidak salah dengan melihat timeline pembangunan infrastruktur militer militer di Laut Tiongkok Selatan. Pada gambar di bawah, terlihat bahwa RRT ( warna merah) lebih sering meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur militernya sejak 2013. Gambar 1 Timeline Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Infrastruktur Militer di Laut Tiongkok Selatan ( U.S. Departement of Defense, 2015) Selain itu, kita juga dapat melihat kembali catatan-catatan tentang kebijakan kekerasan ( coersive policy) oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan.
Selama dekade ‘Kebangkitan yang Damai’, perilaku ‘asertif’ lebih ditunjukan oleh Vietnam dan Filipina, sedangkan perilaku RRT normal-normal saja. Terakhir kali RRT berperilaku ‘agresif’ di Laut Tiongkok Selatan pada Maret 1988.
Akan tetapi sejak 2013, RRT lebih ‘asertif’. Pada Maret 2013 armada People Liberation Army Navy (PLAN) dikabarkan menyerang kapal-kapal nelayan Vietnam yang sedang melaut di dekat Kepulauan Paracel. Pada Desember 2013 kapal pembawa pesawat ( aircraft carrier) Liaoning dikabarkan mengganggu patroli rutin kapal penghancur ( cruiser) USS Cowpens di Laut Tiongkok Selatan. Pada Mei 2014 tercatat bahwa perusahaan minyak nasional RRT melakukan aktivitas pengeboran minyak di dekat Kepulauan Paracel. Terakhir pada Agustus 2014 tercatat bahwa pesawat tempur J-11 milik RRT mengganggu pesawat P-8 Poseidon milik Amerika Serikat yang melakukan patroli rutin di Laut Tiongkok Selatan. Dari beberapa catatan kasus tersebut, perilaku ‘asertif’ RRT dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan.Oleh pemerintah Amerika Serikat, intervensi dalam bentuk pengiriman kapal perang USS Cowpens atau pesawat P-8 Poseidon ke Laut Tiongkok Selatan terkait dengan ‘Operasi Kebebasan Navigasi Laut’ yang dilakukan sejak 1983. Operasi ini ditujukan untuk menyanggah klaim teritorial sepihak RRT atas Laut Tiongkok Selatan dan menjamin kebebasan navigasi dan pelayaran di perairan internasional ini, sebagaimana tertulis dalam UNCLOS 1982.
Akan tetapi oleh sebagian besar pakar hubungan internasional, intervensi Amerika Serikat tidaklah sesederhana untuk menjamin kebebasan, melainkan lebih ditujukan untuk meredam strategi RRT, meredam ‘Kebangkitan yang Damai’ dan SSSJ, terutama karena dapat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Secara filosofis, Mearsheimer (2006) menjelaskan maksud dari ‘mengganggu hegemoni Amerika Serikat’, bahwa ‘Kebangkitan yang Damai’ seperti selama ini ditegaskan RRT adalah sesuatu yang tidak logis. Konsekuensi logis dari ‘Kebangkitan yang Damai’ hanya perang di masa depan, karena RRT akan terlibat dalam sebuah kompetisi keamanan yang intens dan kompleks dengan Amerika Serikat. Selain itu, sebagai aktor yang rasional, Amerika Serikat tidak akan menoleransi kompetisi lebih jauh dengan RRT.
Secara praktis, pernyataan Kaplan (2010) memperkuat penjelasan Mearsheimer (2012). Jika Amerika Serikat menyerah pada klaim sepihak RRT atas Laut Tiongkok Selatan maka aliansi-aliansi tradisional Amerika Serikat di Asia Pasifik secara perlahan akan merapat ke RRT. Atau Allison (2017) yang lebih menegaskan lagi bahwa hubungan Amerika Serikat dan RRT di masa depan kemungkinan besar terjatuh dalam ‘Perangkap Thucydides’, yaitu kondisi dimana negara yang sedang bangkit ( rising power) akan membuat negara yang sedang berkuasa ( established power) akan melakukan segala upaya untuk meredam kebangkitan negara tersebut. Konsekuensi dari kondisi ini adalah eskalasi konflik yang meningkat sampai pada tingkatan perang.
Memang ada pakar-pakar lain yang menganggap ‘Kebangkitan yang Damai’ tidak selalu mengancam Amerika Serikat sebagai hegemoni. Buzan dan Cox (2013) misalnya, menyebut ‘Kebangkitan yang Damai’ sebagai sesuatu yang masuk akal. Adapun dalam kasus RRT, kebangkitan ini berada dalam tingkatan ‘hangat’ ( warm or positive peaceful rise) yaitu bangkit di tengah lingkungan yang bersahabat dengan tingkat ancaman yang rendah. Disini peneliti perlu menambahkan, bahwa Buzan dan Cox tidak menutup kemungkinan-kemungkinan lain di masa depan. Ketika kebangkitan RRT dapat berada dalam tingkatan ‘panas’ ( warlike rise) dimana kebangkitan malah akan memicu perang. Atau pada tingkatan ‘dingin’ ( cold or negative peaceful rise) ketika RRT bangkit di tengah lingkungan yang bermusuhan dengan tingkat ancaman yang tinggi.
Dalam penelitian pada 2012, peneliti membuktikan bahwa hegemoni Amerika Serikat memang terancam oleh kebangkitan RRT. Lebih lanjut lagi, intervensi Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan merupakan sebagian dari implementasi strategi ‘ Rebalancing Towards Asia’. Dimana strategi ini ditujukan untuk meredam kebangkitan RRT yang dapat dicapai melalui implementasi strategi ‘Untaian Mutiara’ atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama SSSJ. Lima tahun lalu, strategi ‘ Rebalancing Towards Asia’ adalah inti dari segala upaya Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional dan menjamin keamanan nasional. Dalam sektor ekonomi, strategi ini terlihat dari kerjasama ekonomi Trans Pasific Partnership (TPP).
Lebih jauh lagi, dalam sektor militer, Amerika Serikat sedang bersiap-siap memindahkan armada militer dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik. Pemindahan ini terlihat dari rencana penempatan lebih dari 60% angkatan laut di Asia-Pasifik, pengiriman marinir ke Australia, peningkatan kerjasama militer dengan Singapura dan Jepang, dan pembukaan kembali pangkalan militer di Filipina. Gambar 2 Kebijakan Militer dalam Rebalancing Towards Asia Akan tetapi kondisi sekarang berbeda. Di Washington, rejim pemerintahan Obama berganti rejim pemerintahan Trump. Strategi Amerika Serikat tidak lagi soal ‘ Rebalancing Towards Asia’, melainkan ‘ America First’.
Tidak sampai seratus hari Trump memerintah, Amerika Serikat secara resmi keluar dari TPP. Selain itu, sudah setahun lebih tidak ada kabar lagi soal rencana-rencana pemindahan pasukan karena Trump menolak untuk melanjutkan kebijakan ‘ rebalancing’ ke Asia-Pasifik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan alasan perubahan strategi Amerika Serikat dari rejim Obama ke rejim Trump dalam konteks persaingan dengan RRT.
Mengapa Trump mengubah strateginya dalam menghadapi kebangkitan RRT? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan strategi SSSJ dalam ‘kacamata’ seorang geostrategis dan realis ofensif. Dari sekian banyak teori dalam hubungan internasional, peneliti menganggap realisme ofensif yang ditulis John H. Mearsheimer (2001) dalam The Tragedy of International Politics-lah yang paling sesuai untuk menjelaskan perilaku RRT sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik. Setidaknya ada beberapa asumsi terkait perilaku negara menurut teori realisme ofensif: Pertama sistem internasional adalah anarki, bahwa tidak ada pemerintah dalam pemerintah.
Lalu negara tidak pernah tahu soal intensi negara lain terhadap mereka, dengan kata lain negara selalu merasa ‘terancam’. Kemudian ‘bertahan hidup’ ( survival) adalah tujuan utama negara dalam sistem internasional.
Bahwa satu-satunya cara bertahan hidup dengan meningkatkan power dan menjadi hegemon di kawasan. Terakhir, negara adalah entitas yang rasional dan instrumental. Negara akan berpikir strategis tentang kondisi mereka, serta memilih strategi yang tepat untuk bertahan hidup. Peneliti juga akan menjelaskan posisi strategis Laut Tiongkok Selatan dalam strategi SSSJ.
Bagaimanapun juga, perilaku RRT makin asertif di perairan ini. Selain itu, perairan ini masih menjadi tempat dimana Amerika Serikat ‘mengganggu’ RRT dengan konsisten. Mengapa Amerika Serikat mengganggu di Laut Tiongkok Selatan, tidak di perairan lain? Ketiga, peneliti akan menjelaskan konsekuensi strategis bagi Indonesia yang muncul dari dinamika hubungan RRT dan Amerika Serikat. Bagaimana strategi Indonesia merespon dinamika ini dengan tepat? Strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’: Tinjauan Realisme Ofensif.
Sebagai salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik, RRT akan berperilaku rasional, yaitu mencari power dengan maksimal ( maximalization of power) dengan tujuan menjadi hegemon di kawasan ini. Mengapa di kawasan?
Karena sejarah mencatat, untuk menjadi hegemon di dunia hampir tidak mungkin dilakukan. RRT dapat disebut sebagai hegemon ketika RRT menjadi satu-satunya ‘kekuatan besar’ ( great powers) di kawasan. Bagi peneliti, setidaknya RRT telah memenuhi tiga dari empat syarat, untuk menjadi hegemon: Pertama, militernya kuat. RRT adalah kekuatan militer terbesar nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Pencapaian ini tidak terlepas dari kesuksesan RRT yang melakukan modernisasi armada laut dan udara serta melakukan revolusi strategi militer mereka sejak 1980-an sampai sekarang. Kedua, ekonominya kokoh. RRT juga merupakan kekuatan ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat.
Pencapaian ini tidak terlepas dari kesuksesan RRT melakukan reformasi ekonomi dalam tiga tahap besar: melakukan reforma agraria (1981-1990), menarik investasi asing (1991-2000), dan melakukan liberalisasi perdagangan (2001-sekarang). Ketiga, mempuyai senjata nuklir. Seperti dijelaskan Chase (2015), RRT adalah salah satu dari beberapa negara yang mempunyai senjata nuklir yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Sebelum menjadi hegemon di kawasan, RRT harus menjadi ‘hegemon potensial’ terlebih dahulu. Dalam istilah peneliti, hegemon potensial adalah negara-negara besar yang belum menjadi paling besar di kawasan, atau negara-negara kuat yang belum menjadi paling kuat (karena yang paling kuat adalah hegemon). Cara mendekteksi negara mana yang menjadi hegemon potensial dengan melakukan perbandingan kekuatan militer dan ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain di kawasan. Jika terdapat perbedaan besar, maka negara tersebut merupakan hegemon potensial di kawasan.
Melihat kondisi saat ini, hegemon hanya ada di kawasan Amerika Utara dan Selatan, yaitu Amerika Serikat. Di Eropa belum ada hegemon, melainkan hegemon potensial, karena Inggris, Perancis, Jerman dan (mungkin) Rusia secara relatif memiliki power yang sama. Kondisi tidak jauh berbeda terlihat di Asia-Pasifik. Secara relatif terdapat hegemon potensial seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT dan (mungkin) India dan Rusia. Sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik.
RRT akan berperilaku rasional dan instrumental dalam sistem internasional. RRT akan instrumental dengan perumusan dan implementasi strategi-strategi yang ditujukan untuk survival. RRT akan rasional dengan memilih strategi-strategi mana yang menjadi prioritas untuk bertahan hidup. Bagi seorang realis ofensif, terdapat dua pilihan utama terkait strategi. Strategi pertama bersifat defensif karena bertujuan untuk menghalau dan mencegah negara lain melakukan hal-hal yang dianggap mengancam bagi suatu negara. Turunan dari strategi pertama adalah ‘penyeimbangan’ ( balancing), ‘penghindaran’ ( buck-passing) dan ‘penguntitan’ ( bandwagoning).
Sedangkan strategi kedua bersifat ofensif karena bertujuan untuk menghancurkan negara lain yang dianggap mengancam tadi. Beberapa turunan dari strategi kedua adalah ‘perang dan penaklukan’ ( war and conquest), ‘provokasi’ ( bait and bleed), ‘pemerasan’ ( blackmail) dan ‘pertumpahan darah’ ( bloodletting). Menimbang fakta RRT sedang gencar-gencarnya dengan SSSJ. Menurut peneliti, RRT sedang melanjutkan implementasi strategi yang defensif dalam bentuk ‘penyeimbangan’. Satu dekade yang lalu, dunia lebih mengenal strategi defensif ini dengan istilah ‘Kebangkitan yang Damai’ ( Peaceful Rise/Peaceful Development).
Lima tahun lalu, dengan mengutip istilah Booz Allen Hamilton, peneliti menyebut strategi defensif ini ‘Untaian Mutiara’ ( String of Pearls). Sekarang dunia mengenalnya dengan istilah ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ ( One Belt, One Road). Secara umum, ‘penyeimbangan’ dilakukan melalui instrumen kebijakan-kebijakan dalam negeri dengan tujuan meningkatkan ketahanan negara ( internal balancing), baik dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun kekuatan militer atau membuat senjata nuklir. Selain itu, ‘penyeimbangan’ juga dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan luar negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas hubungan diplomasi dengan negara lain ( external balancing), baik dengan cara membentuk aliansi militer, membentuk rejim ekonomi, serta berpartisipasi aktif dalam kerjasama-kerjasama bilateral dan multilateral. Adapun sampai sekarang, peneliti menganggap RRT telah melakukan implementasi ‘penyeimbangan’ dengan sukses. Setidaknya terdapat beberapa alasan terkait tesis ini. Pertama, secara prinsip ‘penyeimbangan’ adalah strategi yang ditujukan untuk ‘mengontrol’ distribusi power kepada negara-negara yang dianggap mengancam.
Harapannya, kondisi balance of power dapat terjaga karena power telah terdistribusi dengan merata pada setiap negara. Melalui ‘penyeimbangan’ RRT dapat ‘mengontrol’ distribusi power kepada Amerika Serikat dengan menahan power yang dicari Amerika Serikat dalam sistem internasional, serta mengurangi power yang dimiliki Amerika Serikat. Dampak ‘penyeimbangan’ terlihat dalam kasus-kasus seperti: meningkatnya defisit perdagangan antara kedua negara, keluarnya Amerika Serikat dari TPP dan batalnya rencana-rencana terkait ‘ military pivot’ di Asia-Pasifik. Dalam kondisi power yang ‘kekurangan’ dan ‘tertahan’, dapat dipahami keputusan Presiden Trump yang mengubah strategi ‘ Rebalancing Towards Asia’ menjadi ‘ America First’ Dari yang selama ini lebih ‘melihat keluar’ ( outward looking) sekarang lebih ‘melihat kedalam’ ( inward looking). Peneliti melihat kunci kesuksesan strategi ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT selama ini adalah membangun pondasi ekonomi dalam negeri dengan konsisten dan meredam ‘nafsu’ politik luar negeri sampai pada momen tertentu. Sejak pertama kali RTT melaksanakan reformasi ekonomi pada 1978, Amerika Serikat telah berperang beberapa kali, baik di Irak, Afghanistan dan Suriah. Sedangkan RRT?
Tidak ada sama sekali. RRT tetap fokus dengan reformasi ekonominya. Atau ketika Amerika Serikat bermusuhan dengan Iran, Libya dan Korea Utara. RRT malah mendukung negara-negara tersebut dari belakang layar, melakukan strategi lain yang disebut ‘penghindaran’ ( buck-passing). RRT tidak kekurangan power ketika Amerika Serikat kekurangan power. RRT juga tidak kekurangan power ketika Amerika Serikat mengambil power yang terdistribusi ketika sistem internasional ‘bergerak’ atau ‘bergejolak’ ketika perang. Bahkan RRT mampu mengambil power yang terdistribusi dalam sistem ketika Amerika Serikat sedang berkurang power-nya.
Pada prinsipnya, ketika power suatu hegemon potensial berkurang, maka power hegemon potensial lain akan bertambah, sesuai dengan hukum alam. Akan tetapi hukum ini hanya pasti terjadi dalam sistem internasional bipolar –dimana terdapat dua hegemon. Menimbang sistem internasional di Asia-Pasifik bersifat multipolar, karena terdapat lebih dari dua hegemon potensial. Akan cukup sulit untuk memastikan power yang berkurang dari Amerika Serikat –sebagai salah satu hegemon potensial, hanya terdistribusi ke RRT, karena terdapat kemungkinan power terdistribusi ke Jepang, India atau Rusia –hegemon potensial lain di kawasan Asia-Pasifik. Akan tetapi selama ini RRT sukses mengambil distribusi power tersebut, atau dengan kata lain sasaran ‘penyeimbangan’ tercapai, setidaknya sampai sekarang.
Alasan kedua, taktik dalam ‘penyeimbangan’ adalah ‘penyeimbangan’ kedalam dan keluar. Dalam hal ini, RRT mampu melakukan implementasi ‘penyeimbangan’ kedalam dan keluar yang sinergis. Bahkan dalam beberapa kasus, terlihat RRT melakukan implementasi strategi ‘penghindaran’.
Sinergi dalam ‘penyeimbangan’ dapat dilihat dari pembangunan perekonomian di dalam negeri yang dibarengi dengan diplomasi ekonomi keluar. Bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri RRT yang berbasis pada industrialisasi kemudian dibarengi dengan diplomasi ekonomi di negara-negara lain untuk mencari sumber daya alam sebagai bahan baku industri dalam negeri. Diplomasi ekonomi juga ditujukan untuk membuka pasar bagi produk-produk dari industri dalam negeri RRT. Maka pertumbuhan ekonomi meningkat tajam, atau dengan kata lain pondasi ekonomi RRT perlahan-lahan terbangun dengan kokoh. Tidak heran RRT mampu melakukan modernisasi militer secara besar-besaran.
Tidak heran juga RRT berani membiayai proyek infrastruktur di negara-negara lain. Seperti yang terlihat pada kasus-kasus dalam implementasi strategi ‘Kebangkitan yang Damai’ dan ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ sekarang. Sejarah mencatat kesuksesan ‘penyeimbangan’ seperti RRT saat ini sama dengan ‘penyeimbangan’ yang dilakukan Amerika Serikat melalui “Marshall Plan” setelah Perang Dunia II.
Alasan ketiga, RRT melakukan implementasi strategi ‘penyeimbangan’ dengan mengacu pada hitung-hitungan geostrategi yang matang. Peneliti akan membahas lebih dalam tentang hal ini dalam sub-bab selanjutnya. Strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’: Tinjauan Geostrategi. Strategi SSSJ dapat dipahami sebagai strategi geopolitik dan geoekonomi yang dapat dipecah kedalam dua sub-strategi. Pertama, strategi ‘Jalur Sutera’/JS atau ‘strategi darat’ yang membentang dari RRT melewati kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Eropa Timur sampai Eropa Barat.
Instrumen utama strategi JS adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Baik berupa jalan raya, jalan bebas hambatan atau jalur kereta api.
Gambar 3 Strategi “Satu Sabuk, Satu Jalur” (Xinhua, 2015) Kedua, strategi ‘Jalur Sutera Maritim’/JSM atau ‘strategi laut’ yang membentang dari RRT melewati kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Barat, Eropa Selatan sampai Eropa Barat. Selain itu ruang lingkup dalam JSM termasuk perairan-perairan seperti Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Teluk Bengal, Samudera Hindia, Teluk Persia, Teluk Aden, Laut Merah dan Laut Mediterania. Berbeda dari strategi yang pertama, instrumen utama dalam strategi JSM adalah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa jalur kereta api dan pelabuhan. Serta kebijakan militer berupa pembangunan pangkalan laut dan udara serta pelaksanaan patroli maritim, terutama di Laut Tiongkok Selatan, Teluk Bengal dan Samudera Hindia. Beberapa titik strategis ( strategic spot) yang termasuk dalam rencana pembangunan pangkalan laut dan udara adalah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan, Sittwe di Myanmar, Chittagong di Bangladesh, Gwadar di Pakistan dan Djibouti di Afrika Timur. Berbicara geostrategi adalah berbicara soal dominasi.
Peneliti melihat kedua sub-strategi SSSJ terkait erat dengan prinsip-prinsip utama dalam teori ‘ Heartland’ dan ‘ Rimland’ tentang dominasi global yang diajukan Halford Mackinder pada 1905 dan Nicholas John Spykman pada 1944. Mackinder berpendapat siapapun yang menguasai wilayah Eurasia akan mendominasi dunia. Sedangkan Spykman menganggap siapapun yang menguasai wilayah pesisir disekeliling Eurasia akan menguasai dunia. Gambar 4 Heartland dan Rimland Dengan panduan teori ‘ Heartland’ dan ‘ Rimland’, Kita akan memahami bahwa strategi JS baik langsung maupun tidak langsung ditujukan RRT untuk mendominasi geopolitik dan geoekonomi di Eurasia.
Sedangkan strategi JSM untuk mendominasi geopolitik dan geoekonomi di wilayah periphery Eurasia. Menimbang prinsip realis ofensif bahwa negara adalah entitas rasional dan instrumental. Maka sebagai entitas yang rasional, peneliti berasumsi RRT lebih memprioritaskan dominasi atas ‘ Rimland’ dibanding ‘ Heartland’. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Sebagai perbandingan, Uni Soviet menguasai ‘ Heartland’ dan Amerika Serikat menguasai ‘ Rimland’ Selain itu, ketika Inggris menjadi hegemon pada abad ke 19.
Wilayah kekuasaan Inggris terletak di ‘ Rimland’ membentang dari Arab Saudi, Irak, Iran, India Besar (India dan Pakistan), Burma, Malaysia, Singapura dan Tiongkok. Gambar 5 Wilayah Kekuasaan Inggris di Abad ke-19 sampai awal Abad ke-20.
Kedua, dalam hitung-hitungan ‘kasar’ peneliti, sebenarnya ‘ Heartland’ telah dikuasai oleh RRT, terutama melalui organisasi regional Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan aliansi tradisionalnya dengan Rusia. Hitung-hitungan ini makin terbukti kebenarannya dengan melakukan perbandingan ancaman-ancaman yang terdapat di ‘ Heartland’ dengan di ‘ Rimland’. Di ‘ Heartland’ RRT hanya akan ‘bertarung’ dengan Rusia. Menimbang fakta bahwa Rusia merupakan aliansi ‘tradisional’ RRT. Dalam skenario paling buruk, kemungkinan eskalasi konflik antara kedua negara –dengan mengutip istilah Buzan hanyalah konflik yang ‘dingin’ sampai ‘hangat’, atau dengan kata lain, hampir tidak mungkin sampai pada tingkatan perang. Sedangkan di ‘ Rimland’ RRT menghadapi ‘pertarungan’ yang jauh lebih kompleks, terutama karena menghadapi Jepang dan Amerika Serikat. Negara pertama merupakan kompetitor ‘tradisional’ RRT di Asia Timur dan Asia Tenggara pada hampir seluruh sektor kehidupan negara-bangsa (ekonomi, politik, budaya dll).
Sedangkan negara kedua –selain posisinya sebagai hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik, juga terbukti sering membantu negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan RRT di Laut Tiongkok Timur, Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan. Negara-negara ini termasuk Jepang, Taiwan, Filipina dan Vietnam. Gambar 6 Eksistensi Amerika Serikat di Jalur Sutera Maritim Selain ancaman yang berasal pertarungan pengaruh. Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap ancaman yang terkait integritas teritorial.
Di ‘ Heartland’, ancaman ini berasal dari kelompok pemberontak di Xinjiang dan Tibet. Akan tetapi sampai saat ini, Beijing masih mengontrol kedua wilayah dengan kuat. Peneliti sendiri menganggap kemungkinan Xinjiang untuk lepas tergolong ‘sangat kecil’. Selain karena wilayah ini telah resmi dijadikan koridor utama dalam strategi JS dimana Xinjiang akan menjadi pintu utama RRT ke kawasan Asia Tengah. Di masa depan, Beijing lebih cenderung memilih pendekatan ekonomi (meningkatkan pertumbuhan ekonomi) untuk meredam pemberontakan disana.
Adapun di ‘ Rimland’ ancaman integritas teritorial dapat disebut terlalu kompleks. Taiwan a.k.a Republik Tiongkok masih mengklaim ‘berbeda’ dengan RRT. Jepang tetap bersikukuh atas kedaulatan di Kepulauan Senkaku dan Laut Tiongkok Timur. Kemudian di Laut Tiongkok Selatan, klaim teritorial Tiongkok tidak saja ditolak mentah-mentah oleh Vietnam dan Filipina yang bertetangga secara geografis. Baik Amerika Serikat, Inggris, Australia dll juga menaruh perhatian terhadap dinamika dalam perairan ini. Bilamana SCO eksis di ‘ Heartland’, maka ASEAN eksis di ‘ Rimland’. Sayangnya pengaruh RRT di ASEAN tidak sebesar pengaruh di SCO.
Peneliti dapat mengetahui hal ini dari perbandingan pengaruh kebijakan luar negeri SCO dan ASEAN. Selain itu juga dapat dibuktikan dengan melihat kondisi internal ASEAN disebut masih mengalami dualisme dalam menentukan keberpihakan. Beberapa negara jelas-jelas memihak Beijing, seperti Myanmar dan Kamboja. Beberapa lagi tersirat pro ke Washington, seperti Filipina dan Vietnam. Lainnya memilih untuk ‘netral’ atau lebih tepat disebut berada dalam posisi ‘dua kaki’, seperti halnya Indonesia. Terakhir, terkait eksistensi ancaman-ancaman non-tradisional. Di ‘ Heartland’, ancaman utama berasal dari eksistensi kelompok pemberontak di Xinjiang dan permasalahan keamanan energi terkait kawasan Asia Tengah.
Sedangkan di ‘ Rimland’ RRT tidak hanya berurusan dengan ancaman-ancaman kelompok terorisme transnasional di Malaysia, Indonesia dan Filipina yang terkait dengan pemberontak Xinjiang. Akan tetapi juga permasalahan keamanan energi dan integritas teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Dengan melakukan perbandingan kondisi antara ‘ Heartland’ dan ‘ Rimland’, akan sangat logis ketika RRT hanya membangun pangkalan militer pada wilayah-wilayah dalam JSM. Kita juga dapat memprediksi bahwa di masa depan, RRT akan meletakkan prioritas pada JSM daripada JS. Prioritas RRT pada JSM dapat dipahami lagi dengan membahas perairan yang paling strategis dalam strategi ini, yaitu Laut Tiongkok Selatan dengan lebih mendalam. Posisi Strategis Laut Tiongkok Selatan Dalam Strategi ‘Jalur Sutera Maritim’ Peneliti menganggap posisi Laut Tiongkok Selatan strategis karena perairan ini merupakan ‘awal dan akhir’ atau ‘hulu dan hilir’ dalam strategi JSM.
Selain itu, RRT memang sangat tergantung pada Laut Tiongkok Selatan dalam konteks perdagangan dan energi. Menimbang posisi strategis ini, ditambah kemungkinan terjadi skenario-skenario terburuk seperti blokade laut atau invasi dari ‘Timur’ membuat Beijing hanya memiliki pilihan kebijakan yang terbatas: harus mempertahankan Laut Tiongkok Selatan dan harus mengontrol perairan tersebut untuk mengurangi ancaman dan risiko. Gambaran peneliti tentang blokade laut adalah seperti ini: Jika keamanan Laut Tiongkok Selatan terganggu, maka kapal pengangkut barang dari RRT harus memutar melewati Laut Filipina Timur, Selat Makasar untuk menuju Selat Malaka kemudian melanjutkan pelayaran ke Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa Selatan. Kondisi sama juga berlaku bagi kapal tanker yang membawa crude oil dan Liquid Natural Gas (LNG) dari Timur Tengah dan Afrika Timur menuju RRT. Dampak yang paling terasa adalah biaya yang membengkak dan waktu yang meningkat, khususnya untuk komoditas energi seperti batubara, crude oil dan LNG. Konsekuensi logis dari dampak tersebut adalah kelangkaan energi, berlanjut pada pertumbuhan ekonomi yang melambat, berlanjut pada instabilitas politik di dalam negeri.
Dengan kata lain, ancaman bagi rejim Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai penguasa. Peneliti dapat menyederhanakan penjelasan tersebut dalam istilah: keamanan energi tergolong vital bagi RRT. Mengontrol energi akan meningkatkan power. Meningkatnya power akan menjamin keamanan. Terjaminnya keamanan dari ancaman eksternal dan internal merupakan sesuatu yang mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas.
Keamanan energi terkait dengan empat aspek utama, yaitu ketersediaan ( availability), kemudahan akses ( accessibility), keterjangkauan harga ( affordability) dan penerimaan masyarakat ( acceptance). Adapun Laut Tiongkok Selatan dapat ditinjau dari keempat aspek tersebut dengan alasan-alasan: Jika ditinjau dari aspek ketersediaan. Maka kita akan mengetahui bahwa jumlah cadangan terduga gas alam di Laut Tiongkok Selatan tergolong melimpah. Menurut estimasi Energy Information Administration (2013), di Laut Tiongkok Selatan terkandung 11 miliar barel minyak (mulai 5 miliar barel estimasi paling endah, sampai 22 miliar barel estimasi paling tinggi) dan 190 triliun kaki kubik (mulai 70 triliun kaki kubik estimasi paling rendah, sampai 290 triliun kaki kubik estimasi paling tinggi) yang dapat dikelola secara komersial. Sebagai gambaran, jumlah cadangan minyak sebesar ini sama dengan yang terdapat di Meksiko, dan cadangan ga ssebesar ini sama dengan yang terdapat di Eropa (kecual Rusia). Kemudian ditinjau dari aspek kemudahan akses. Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur utama bagi tanker crude oil dan LNG dari Timur Tengah, Indonesia dan Australia ke RRT dan negara-negara Asia Timur lain.
Menurut perhitungan Energy Information Administration (2013) sekitar 10 persen dari kebutuhan energi RRT diangkut tanker yang melalui Laut Tiongkok Selatan Jika ditinjau dari aspek keterjangkauan harga. Secara umum mengangkut LNG dengan kapal tanker akan jauh lebih murah dibandingkan mengirim gas tersebut melalui pipa. Memang ada best practices dalam pengiriman gas melalui pipa, misalnya dalam kasus pengiriman gas alam dari Siberia ke Eropa.
Akan tetapi dalam penilaian kasar, risiko politik pada wilayah yang membentang dari Siberia ke Eropa tergolong kecil. Berbeda halnya jika membangun pipa gas dari Timur Tengah ke Tiongkok, dimana risiko politiknya besar karena melewati negara-negara yang tidak stabil, belum lagi ancaman-ancaman dari kelompok teroris yang eksis di Pakistan dan Afghanistan. Terakhir ditinjau dari aspek penerimaan masyarakat. Bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang diklaim oleh RRT dan mendapat dukungan dari rakyatnya. Salah satu buktinya adalah perhatian media-media nasional di RRT terhadap isu Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, peneliti menganggap secara tidak langsung keberhasilan membangun instalasi pengeboran gas di Laut Tiongkok Selatan akan berpengaruh terhadap nasionalisme rakyat Tiongkok. Kondisi yang sama terjadi di Indonesia, bilamana Pertamina berhasil menguasai dan melakukan aktivitas pengeboran di perairan-perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim RRT di Laut Tiongkok Selatan, atau perairan Ambalat yang disengketakan dengan Malaysia, atau yang terakhir Blok Masela di Laut Arafura yang berbatasan dengan teritorial Australia.
Media-media nasional akan menuliskan berita-berita yang terkait dengan nasionalisme sumber daya alam. Menimbang alasan-alasan ini, maka tidak heran strategi ‘penyeimbangan’ internal dengan taktik militer dipusatkan pada kepada perairan ini. Selama beberapa tahun kebelakang, armada laut People Liberation Army Navy (PLAN) baik berupa kapal selam ( submarine), kapal penghancur ( destroyer) dan kapal pembawa pesawat ( aircraft carrier) sering melakukan penjagaan di perairan ini Perubahan Strategi Amerika Serikat Dari Rejim Obama ke Rejim Trum: Tinjauan Realisme Ofensif Pada sub-bab sub-bab sebelumnya, telah dijelaskan tentang SSSJ sebagai strategi ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT kepada Amerika Serikat. Sebagai salah satu hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat tentu mempunyai counter strategi terhadap ‘penyeimbangan’ yang dilakukan RRT. Terlebih seperti yang telah dituliskan di awal, bahwa sebagian besar pakar hubungan internasional lebih menganggap kebangkitan RRT dapat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di dunia.
Dalam sub-bab ini, peneliti lebih terfokus untuk mengulas transisi strategi di Washington dari rejim Obama ke rejim Trump. Dalam penelitian pada tahun 2012 lalu, peneliti telah membuktikan rejim Obama lebih bertumpu pada strategi ‘provokasi’ ( bait and bleed) daripada strategi lain. Kentalnya nuansa ‘provokasi’ dalam strategi ‘ Rebalancing Towards Asia’ terlihat dari hal-hal seperti: pembentukan TPP sebagai tandingan SSSJ, pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan di Washington soal ancaman perilaku asertif RRT di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, dan paling utama adalah upaya-upaya mereka untuk meningkatkan kerjasama militer, menempatkan pasukan dan membangun pangkalan militer di negara lain. Pada prinsipnya, dengan melakukan ‘provokasi’, Amerika Serikat dapat meningkatkan power ketika power RRT berkurang dalam konflik atau perang. Untuk dapat melakukan ‘provokasi’, selain terdapat negara yang melakukan provokasi ( bait), perlu ada negara yang terprovokasi ( bleed).
Dalam catatan sejarah, strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat kepada Uni Soviet selama Perang Dingin. Provokasi lebih banyak dengan ‘ancaman semu’ bahwa terdapat kemungkinan besar Amerika Serikat akan melakukan pre-emptive strike kepada Uni Soviet. Uni Soviet merepon provokasi tersebut dengan peningkatan anggaran pertahanan dan pembangunan kemampuan militer yang ofensif. Lebih jauh lagi, Uni Soviet melakukan perang yang ‘memaksa’ di Afghanistan. Meningkatkan anggaran pertahanan secara tidak langsung mengurang anggaran sektor-sektor lain. Pembangunan kemampuan militer yang ofensif memakan biaya mahal, termasuk dengan melakukan perang.
Sejak 1980-an Uni Soviet mulai mengalami defisit budget, perekonomian makin memburuk. Sampai pada awal 1990-an, Uni Soviet bubar dan resmi kalah dalam Perang Dingin. Dua dekade kemudian, ‘provokasi’ dicoba lagi oleh rejim Obama. Akan tetapi gagal total, terutama karena RRT tidak termakan ‘provokasi’ yang dilancarkan Amerika Serikat. Selain karena belajar dari pengalaman Uni Soviet, dari penjelasan peneliti tentang strategi ‘penyeimbangan’ di awal tulisan, RRT terlihat memiliki fokus dan konsistensi melakukan ‘penyeimbangan’, setidaknya sampai saat ini.
Tidak heran, ketika rejim Trump berkuasa, orientasi strategi Amerika Serikat berubah, dari ‘ Rebalancing Towards Asia’ menjadi ‘ America First’. Secara tersirat, strategi ini adalah bentuk ‘penyeimbangan’. Hal ini terlihat dari beberapa hal, seperti keinginan rejim Trump untuk membangun kembali pondasi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis finansial global pada 2007, keinginan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan upaya membangun diplomasi yang lebih baik dengan RRT. Peneliti sendiri memprediksi rejim Trump tidak hanya melakukan ‘penyeimbangan’ melainkan juga ‘penghindaran’ di masa depan.
Pada prinsipnya, strategi ‘penghindaran’ adalah strategi dimana suatu negara yang merasa terancam (disebut buck-passer) akan menggunakan negara-negara lain sebagai ‘penghalang’ (disebut buck-catcher) untuk menghadapi negara yang mengancam. Sekilas mirip dengan ‘provokasi’, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek yang diprovokasi. Dalam hal ini, yang menjadi objek provokasi dalam ‘penghindaran’ adalah negara ‘penghalang’ Dengan harapan, negara ‘penghalang’ akan berperang atau berkonflik dengan negara yang mengancam. Mearsherimer (2001) menjelaskan bahwa keberhasilan strategi ‘penghindaran’ tergantung pada beberapa hal: Pertama, negara yang melakukan ‘penghindaran’ membangun hubungan diplomasi yang baik dengan negara yang mengancam, atau minimal tidak melakukan provokasi kepada negara tersebut.
Harapannya, negara tersebut akan terfokus pada negara negara ‘penghalang’ yang telah ditentukan. Kedua, negara yang melakukan ‘penghindaran’ tetap menjalin hubungan diplomasi dengan negara ‘penghalang’, akan tetapi hubungan tersebut tidak lebih baik dibanding dengan negara yang mengancam. Hal ini dikarenakan negara yang terancam tidak ingin terlibat konflik dengan negara yang mengancam, atau dianggap memihak negara ‘penghalang’ oleh negara yang mengancam. Ketiga, negara yang melakukan penghindaran membantu upaya-upaya peningkatan power negara ‘penghalang’ dari belakang layar. Bagi peneliti, strategi ‘penghindaran’ lebih tepat untuk diimplementasikan di kawasan Asia-Pasifik. Karena sistem internasional di kawasan Asia-Pasifik cenderung mengarah pada sistem multipolar yang tidak seimbang. Konsekuensi melakukan ‘penghindaran’ dlam sistem internasional yang seperti ini adalah negara-negara ‘penghalang’ akan bergabung membangun aliansi atau menambah kedekatan dengan asumsi negara yang mengancam adalah satu dan ancamannya besar.
Dalam skenario peneliti, strategi ‘penghindaran’ cocok diimplementasikan kepada negara-negara di Asia Tengara yang sedang bersengketa dengan RRT. Selain itu, cocok juga diimplementasikan kepada Jepang yang bersengketa dengan RRT di Laut Tiongkok Timur. Dampak Strategis Bagi Indonesia Penjelasan peneliti tentang interaksi strategi antara RRT dan Amerika Serikat ini berguna bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis di masa depan.
Penjelasan ini juga makin membuktikan kebenaran perang proxy yang terjadi di Asia Tenggara. Melihat kondisi saat ini, peneliti dapat menyarankan untuk konsisten melakukan ‘penyeimbangan’. Kesuksesan ‘penyeimbangan’ akan terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas militer.
‘Penyeimbangan’ juga akan terlihat dari partisipasi aktif Indonesia dalam SSSJ. Sebagai alternatif, Indonesia juga dapat melakukan ‘penguntitan’. Seperti yang dilakukan rejim Joko Widodo kepada Tiongkok. Akan tetapi strategi ini tidak disarankan jika diimplementasikan dalam waktu yang panjang. ‘Penguntitan’ akan lebih efektif jika dilakukan lebih baik dalam waktu yang pendek. Atau dalam istilah peneliti, dilakukan dengan ‘dinamis’, atau menguntit baik RRT dan Amerika Serikat secara bergantian.
Penutup Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini: Pertama, selama beberapa dekade RRT terbilang berhasil mengimplementasikan strategi ‘penyeimbangan’ dalam konteks ‘Kebangkitan yang Damai’ dan ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’. Kedua, menimbang strategi ‘Satu Sabuk, Satu Jalur’ dapat dibagi menjadi ‘Jalur Sutera’ dan ‘Jalur Sutera Maritim’. Maka prioritas RRT akan terletak pada implementasi ‘Jalur Sutera Maritim’.
Hal ini tidak lepas dari posisi strategis Laut Tiongkok Selatan dalam strategi tersebut, serta eksistensi ancaman di wilayah-wilayah yang berada dalam ruang lingkup strategi tersebut. Ketiga, transisi strategi Amerika Serikat dari ‘Rebalancing Towards Asia’ ke ‘America First’ terjadi karena kegagalan rejim Obama mengimplementasikan nilai-nilai strategi ‘provokasi’ dalam strategi yang pertama. Adapun Trump sedang coba mengimplementasikan nilai-nilai strategi ‘penyeimbangan dalam strategi yang kedua. Terakhir, interaksi strategi antara kedua hegemon potensial di kawasan Asia-Pasifik harus lebih dicermati dengan baik oleh Indonesia karena kental nuansa perang proxy-nya, Dalam hal ini, ketika memilih strategi, ‘penyeimbangan merupakan suatu keharusan, sedangkan ‘penguntitan’ memerlukan satu kecerdikan.
Jurnal ini mengacu pada skripsi peneliti yang berjudul “Ancaman Kerjasama Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara Terhadap Implementasi Strategi ‘Untaian Mutiara’ Republik Rakyat China di Laut China Selatan” untuk mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran pada 2012. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kerangka penelitian yang sama, akan tetapi pertanyaan yang diajukan berbeda dan data-data yang digunakan lebih update. Peneliti adalah Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dengan kekhususan bidang Keamanan Global dan Master Pertahanan Universitas Pertahanan dengan kekhususan bidang Keamanan Energi. Dalam purna waktu, peneliti aktif sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Strategis di Lingkar Studi Strategis. “China’s One Belt, One Road Initiative: Context, Focus, Institutions and Implications” dalam The Chinese Journal of Global Governance 2. Hal 31 National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China. Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road.
Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Yunling, Zhang. “One Belt, One Road: A Chinese View” dalam Global Asia Fall 2015: 10. Hal 8 Ferdinand, Peter. “Westward Ho: The China Dream and ‘One Belt, One Road’: Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping” dalam International Affairs 92:4.
Hal 942 Morrison, W.M. “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges and Implications for the United States” dalam CRS Report for Congress. Ferdinand, Peter. “Westward Ho: The China Dream and ‘One Belt, One Road’: Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping” dalam International Affairs 92:4. Hal 941 Callaghan, Mike dan Hubbard, Paul. “The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the Silk Road” dalam China Economic Journal 9:2.
Hal 118 Weiss, Martin A. ‘Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)’ dalam CRS Report for Congress National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China. Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road. Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Fels, Enrico dan Vu, Truong-Minh. “Introduction: Understanding the Importance of the Disputes in the South China Sea” dalam Power Politics in Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea. New York: Springer. Hal 9 Associated Press.
26 Maret 2013. Hanoi Accuses Chinese of Firing at Boat.
Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Global Times. 18 Desember 2013. Trust-Building Need to Cut The Knot of China-United States Military Ties.Diakses dari 1 Agustus 2017 Deutsche Welle.
24 Agustus 2014. China Defends Interception of U.S. Navy Aircraft. Diakses dari pada 1Agustus 2017.
Mearsheimer, John. “China’s Unpeaceful Rise” dalam Current History 105:690. Hal 160-162 Kaplan, Robert. “The Geoghraphy of Chinese Power: How Fat Will China Reach on Land and Sea?” dalam Foreign Affairs 89:3. Hal 10 Allison, Graham. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?
New York: Knopf. Dagget, Stephen et al. “Pivot to Pasific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia” dalam CRS Report for Congress. Hal 10 New York Times.2017. Trump Abandons Trans-Pasific Partnership, Obama’s Signature Trade Deal. Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Time.
Pentagon Backs a $7.5 Billion Plan to Boost U.S. Mlitary Presence in Asia-Pasific, Report Says.
Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Kaplan, Robert D. Asia’s Cauldron: The South China Sea and The End of a Stable Pasific. New York: Random House Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Hal 38 Global Power Index 2017 Erickson, Andrew S. “Evaluating China’s Conventional Military Power: The Naval and Air Dimensions dalam Assessing China’s Power.
New York: Palgrave MacMilan Godement, Francois. China’s Economic Power: Catching up with the United States by 2025?” dalam Assessing China’s Power. New York: Palgrave MacMilan Chase, Michael S. “Assessing China’s Evolving Nuclear Capabilities” dalam Assessing China’s Power.
New York: Palgrave MacMilan Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Hal 118 Ibid National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of People Republic of China.
Vision and Actions on Jointly Building the Silk Road Economic elt and the 21st Century Maritime Silk Road. Diakses dari pada 01 Agustus 2017 The Economist. Tibet and Xinjiang: Marking Time at the Fringes. Diakses dari www.economist.com/node/16539510 pada 1 Agustus 2017 Grace, Abigail.
“Quantifying China’s Influence on the Shanghai Cooperation Organization” dalam Cornell International Affairs Review 10:1. Hal 1 Forbes.
Asia’s Dilemma: China’s Butter, or America’s Gun? Diakses dari pada 1 Agustus 2017 Caceres, Sigrifido B. Strategic Interests in the South China Sea. London: Routledge. Hal 10 Hayton, Bill. “Something and Nothing: Oil and Gas in the South China Sea” dalam The South China Sea: The Struggle for Power in Asia. London: Yale University Press.
Hal 149; U.S. Energy Information. South China Sea Energy Brief. Diakses dari topics.cfm?fips=scs pada 1 Agustus 2017 Ibid dan Zhang, Jian. 2011 “China’s Energy Security: Prospects, Challenges and Opportunities dalam Working Paper CEAP Visiting Fellows No. Brooking Institution Center for East Asia Policy Studies Morris, Daniel, 2015. Efficent Transportation of Energy.
Perlu diperhatikan, peneliti hanya memberi gambaran umum tentang perbandingan transportasi LNG melalui tanker atau pipa dari sumber yang sangat jauh. Hasilnya, tanker lebih efisien secara biaya. Tesis peneliti berjudul ‘Ancaman Kerjasama Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara dan Strategi ‘String of Pearls; Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan’ Tang, Shao dan Liu, Dong dan Xie, Xi. “The Analysis of the ‘One Belt One Road’ for the Game Between China and United States” dalam 3rd International Conference on Social Sciences and Management. Dari sekian banyak pernyataan yang dibuat pejabat pemerintahan. Peneliti terfokus pada pernyataan Hillary Clinton tentang Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan ini dapat dilihat dalam dokumen yang diunggah wikileaks dalam pada 2013.
Dagget, Stephen et al. “Pivot to Pasific?
The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia” dalam CRS Report for Congress. Hal 10-15 Central Intelligence Agency.
Implications of a Surging Soviet Budget Deficit: An Intelligence Assessment Trump, Donald. Crippled America: How to Make America Great Again. New York: Thresold Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W.
Hal 133-137 Download jurnal ini versi pdf, klik berikut. The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia’s to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources.
Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.
Read more on. By: Adrianus A. Yudianto United Kingdom (UK) is the first state to withdraw its membership in the European Union (EU). This historic moment is also commonly known as Brexit, an abbreviation of the words Britain and exit, referred to the scenario of potential Greece withdrawal from the eurozone following Greece debt crisis. Brexit caused the pound sterling to plummet against other major currencies and David Cameron’s swift resignation from his position as prime minister. It also triggers a possibility of second Scottish referendum and possibility for Northern Ireland’s reunification with the Republic of Ireland.
However, it is still unclear whether UK’s withdrawal will result in peaceful and close ties with EU with reform in many areas or a violent severance of relations between UK and EU. The call for referendum to decide the future of UK in the EU was pushed as far as David Cameron’s remark at the EU Summit in Brussels On December 2015. Even though Cameron suggested that in/out referendum will be held in the following year, he made his position clear in his remarks that continued membership is vital to economic security and to the fight against international terrorism. Brexit campaigners and former London mayor, Boris Johnson, on February 2016 pushed the idea to hold the referendum. On April 2016, Vote Leave was announced as an official campaign to promote UK leaving EU followed by official referendum campaign period across UK. For 4 weeks following the Purdah period starting at the end of May, civil servants of the Central Government and local authorities in UK is forbidden to publish any material related to referendum or release any information that could influence the way the public vote.
A day after polling day, on 24 June 2016, there will be a national declaration of the referendum result after on June 23 rd those who are in favor of UK leaving EU won by 52% to 48%. Aside from Brexit, EU is currently struggling with many issues ranging from increasing influx of immigrants and refugees, recent terrorist attacks, and several members slow recovery from debt crisis. Brexit has dealt a major blow to EU’s stability and cohesion as a regional organization. Thus, UK decision to quit poses a question on whether the EU model of regional integration is still relevant as one of the prominent model of regional integration. United Kingdom and the European Union The decision to quit arguably is not an easy one for both UK and EU.
Being one of the prominent members, UK contributed on average of £13 billion annually. Losing financial contribution from one of its top five donors means an additional burden for each of EU member states.
On the other hand, losing membership will cost UK additional funds to re-enter European market in addition of further negotiations to decide the fate of EU workers in UK, and to establish border control agreement between UK and EU. In addition to economic downturn, Brexit could also lead to other problems concerning UK’s relation with EU and EU member states. Notwithstanding the importance of economic relations between UK and EU, to bring a holistic approach to assess Brexit’s impact to regional integration it is important to look beyond economic relations and at first see how UK politically positions itself from other European members of EU. David Abulafia, an English historian, described the relationship that the United Kingdom has always been a partner of Europe without being a participant of it. He said that Britain has a distinctive way of development compared to its continental neighbors. With vast colonial territory, until the second half of 20 th century, Britain was reluctant to be a part of being a European nation in fear that it would signify the loosening of ties with Commonwealth and a cessation of imperial status.
Britain has its own legal system, which is different from Roman law or Napoleon codes. Britain has also a rather different approach to fascism, anti-Semitism, and communism. When several European countries embraced fascism and communism, such idealist movements had no deep roots in Britain. Even though historically Britain had a rather distant approach to other European nations, in 1946 Winston Churchill, at that time a former prime minister of UK, delivered a speech in Zurich proposing an idea to recreate partnerships between Germany and France, idea of the United States of Europe, and a call to form a Council of Europe. British government is late to embrace Churchill’s idea of a unified Europe. At first, UK rejected the initial invitation by 6 European countries (Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, and Netherlands) to join European Economic Community in 1957 and later joined the Common Market in 1973. In 1975 there was a similar in/out referendum to decide whether UK still being a part of EEC.
The referendum in 197 resulted in Britain decided to keep its membership in the Common Market. European Union as a Unique Regional Organization Regional Organization can be defined as bureaucracies with restricted conditions of membership, with members consist of governments or government representatives.
It is a result of urgencies to work together to tackle their problems. However, EU works beyond that definition. EU does not work solely to provide an arena for its members, but also working as actor, that into some extent, providing guidance for its member states to act accordingly to maintain European Community’s stability. Among all regional organizations, EU stands out as the most distinctive regional organization because of its level of integration and its regional institutions.
There are six institutions under EU which signify this distinction by executing functions beyond its member states’ border within EU’s jurisdiction: European Council, European Commission, European Parliament, European Court of Justice (ECJ), and European Central Bank. Among those six, implementation of policies in EU is carried out by powerful ECJ. It is a political watchdog that controls European Commission and European Parliament. Working in accordance of the treaties constituting the framework of political cooperation within EU, ECJ also functions as a policy-making body that creates law through its case law; it supervises other EU’s institutions and member states to ensure that they adhere to rules set up by EU.
Even though laws and treaties within European Union are results of a democratic process, there are still critics implying that EU and its regional institutions sometimes work above its own member’s jurisdiction and therefore limiting EU member states’ sovereignty. Fraser Cameron wrote an essay in 2010, placing EU model of regional integration as the best leading example for other efforts to achieve closer regional integration. His basis of argument lies on the EU’s ability to recover from economic crisis in 2008 and previous crises before that. He stated that different tiers of integration reflected in exclusion for member countries to opt out of eurozone of Schengen area helped speed up integration in EU. Given the difference of economic growth among its members and its euro-skeptic nature, EU decided it is best to exclude UK and several other members from the eurozone to maintain currency stability. In other hand, it would not help the euro-skeptic UK to diminish its already skeptic view and share the same urge to manifest Churchill’s ideal to unify Europe.
Seek for shared identities among member states still become a quest with unknown destination given its expansion in 2004 to include members with diverse background. It is summarized that there are four tenets of EU, namely the supranational community method, political will to share sovereignty, close relationship between France and Germany as founding members, and consensus of the members to address problems affecting its member states.
Since its inception, EU has been lauded for its supranational model and community method over traditional balance of power approach. There are political will among its founding members to share sovereignty to achieve closer and deeper integration. It is unclear, however, whether latter members of EU share the same sense of belonging toward the idea of a unified European Community. Despite past strife and differences, France and Germany had also been successful to recreate a peaceful relationship among the members of EU. A more accommodative approach to address the problems of its member states also beneficial, even though hesitance to move forward before the majority of EU members agreed to adopt the policy could also led to sustained damage affecting its member state’s people and further creating domino effect.
In the future, he stated that EU will still face several problems, such as fluctuation of energy price, rising commodity price, aging populations, growing labor markets of Asia, and unwillingness of Asian partners to impose the same welfare schemes as EU. Solidarity of eurozone members will still be tested as several members still recovering from debt crisis. Discussions in climate change and energy security will also impose their own challenge as many EU members still have different perspective to address both issues. There is also reluctance coming from European public backed by national politicians for deepening integration and stronger EU. Given its durability to withstand many crises before, EU will recover sooner or later.
It is still undecided, however, the future of UK without EU membership’s privilege and benefits. Given two years to finalize its withdrawal, the fate of UK will be determined by the quality of its government and public to recuperate from some damages caused by Brexit. Lesson Learn for Other Regional Organizations If many things can be learned from EU model of integration, the first two will always be the willingness to create the political will and historic reconciliation among members of regional organization.
Sustained efforts are needed to end conflict or disputes among countries in the region. That rhetoric should be manifested through actions. Otherwise, the idea of integration will just remain a false hope and failed plans. Taking a lesson from Brexit, other regional organizations should revisit their way to pursue regional integration, especially if they adapted the EU model as their benchmark. EU faces a little challenge if any country wants to be a part of the Union, since aspiring members should comply to EU’s already standardized requirements and carry out democracy as political system. Those requirements are stated explicitly within Article 49 of Lisbon Treaty.
However, different approach should be implemented for regional organization with member states coming from different spectrum of diversity. A push for closer and deeper ties among their member states should be achieved through their own formula. Every regional organization also should take note to separate important issues that should be addressed on regional level from specific issues that better be delegated to national parliament. By division of authorities, redundancy could be minimized and chances for regional agreements to undermine national political process could be prevented. There are several cases in EU where public officials are stating their disappointment for non-accommodative regional agreements, fearing that their country’s sovereignty is being violated or reduced. Interests conveyed by top government officials of UK to remain being member of EU did not automatically reflect the majority of their national members of parliament and British public at general.
Those who are in favor of leaving EU do not share the same concern and cultural identity as other European. These led to many problems, including fear of foreigners taking their privilege and incite racist behavior among UK public. By creating a community, shared norms and values should be continually introduced and being fostered. If member states are failed to promote a shared cultural identity as a citizen of the region, then gaps would be created and widened among citizens of its member states.
At last, it is important for a regional organization wanted pursuing integration by democratic means to ensure that its people have proper access to governmental process and balanced information, especially if their vote will affect their lives for years to come. During period of February 2016 to the day of the referendum, the campaign from side in favor of leaving EU is more rigorous than those who want to stay. Several Brexit campaigners even resort to fear mongering campaign, using immigrants as object to instill racism and xenophobia. Ironically, after the official result has been announced, there are five common questions being searched on Google in UK, the second highest one being “What is EU?” The four other questions were asking on what it means to leave EU, member countries of EU, how many member states of EU and what will happen after leaving EU.
All five are questions which supposed to be covered by a proper socialization before referendum takes place. This shows that a large portion of the public have no idea on what they are voting for. By learning from Brexit, every regional organization should take a serious warning that giving opportunity to misinformed voters to make an irreversible, divisive decision is a reckless political move at its best. References: New York Times. Explaining Greece’s Debt Crisis.
17 June 2016. The Telegraph. David Cameron resigns after UK votes to leave European Union. 24 June 2016. Brexit: Nicola Sturgeon says second Scottish independence vote ‘highly likely’. 24 June 2016. EU referendum: Northern Ireland votes to remain.
24 June 2016. The Guardian. EU referendum: David Cameron hints vote could be held summer 2016. 19 December 2015.
Sunday Express. When is the EU referendum 2016? Timeline of all key date and events. 23 June 2016. EU Budget., See also: Germany’s contribution to EU annual budget ‘could rise by £2bn after Brexit’, Brexit would cost German economy up to $50 billion by end – 2017- study, and Financial Times.
How will Brexit result affect France, Germany, and the rest of Europe? David Abulafia. Britain: apart from or a part of Europe?
History Today. The Churchill Society. Winston Churchill speaking in Zurich, 19 th September 1946.
Britain and the EU: a long and rocky relationship. Historical Dictionary of International Organizations.
Plymouth:Scarecrow Press Inc. P lvii and p39 EU. EU institutions and other bodies.
Aksel Hatland and Evel Nilsen. “ Policy making and application of law: free movement of persons and the European Court of Justice” in the Role of International Organizations in Social Policy.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Inc. Pp94-96 Nina Berglund. EU Rules ‘undermine sovereignty’. See also: Miles G.
UK Membership in the European Union: Undermining Parliamentary Sovereignty Cameron, Fraser. The European Union as a Model for Regional Integration. Council on Foreign Relations Press. Polish sovereignty is imperiled after EU criticism: preier says., See also: Miles G.
UK Membership in the European Union: Undermining Parliamentary Sovereignty Kate Ferguson. EU Referendum: Immigrants told to ‘leave UK now’ after ‘divisive and xenophobic’ Brexit movement, Warsi says. The Independent. Ellie Mae O’Hagan. The UK’s ‘Brexit’ Vote is Actually a Referendum of Xenophobia. Global Research., See also: Anyusha Rose.
The Brexit debate has made Britain more racist. Washington Post.
22 June 2016., Leah Donella. Brexit: What’s Race Got to Do with It? Russia Today. Post-Brexit Google stats imply UK voters were clueless at polls. 24 June 2016. Oleh: David Putra Setyawan, S.Kom, M.Si(Han) Sejak bulan Maret 2011, pihak pemerintah Suriah telah terlibat perang sipil dengan partai oposisi. Perang ini dipicu oleh kemarahan penduduk yang memprotes ditahannya 15 anak sekolah.
Selain ditahan, anak-anak tersebut juga dilaporkan disiksa. Namun aksi demo yang dilakukan penduduk tersebut direspon keras oleh aparat pemerintah dengan melepaskan tembakan ke demonstran (BBC, 2015).
Hal tersebut menyebabkan kemarahan penduduk dan kerusuhan mulai menyebar diberbagai tempat di Suriah yang berujung pada penuntutan turunnya Presiden Bashar al-Assad. Meluasnya konflik tersebut menyebabkan banyak munculnya kelompok-kelompok militer kecil yang semuanya bertermpur melawan pemerintah. Diantara mereka, kelompok militer paling besar adalah tentara pembebasan Suriah.
Namun, kelompok tersebut masih kalah jauh dengan pasukan pemerintah. Di sisi lain, kelompok-kelompok tersebut juga tidak bekerja secara terkoordinasi.
Konflik ini terus berlanjut hingga pada 21 Agustus 2013 pemberontak Suriah melaporkan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh rezim pemerintah. Pemerintah Suriah diindikasikan menggunakan roket untuk meluncurkan senjata kimia yang mengakibatkan korban mengalami kejang-kejang, kebutaan, bengkak, maupun mual.
Lebih lanjut, Yayasan Pertahanan Hak Asasi Manusia Suriah menyatakan bahwa penggunaan senjata kimia telah dilakukan oleh rezim Suriah sebanyak 28 kali diantara tanggal 13 Juli dan 21 Agustus. Serangan tersebut melibatkan 85% penggunaan gas Sarin serta penggunaan zat amonia dan CS3 yang menewaskan 1845 orang dan melukai lebih dari 9000 jiwa (Khabar South Asia, 2013). Serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran dalam hukum humaniter internasional yang dengan tegas melarang penggunaan senjata-senjata mematikan dan yang dapat mengakibatkan korban sipil, merusak lingkungan dan penderitaan yang panjang seperti berbahan nuklir, bom tandan dan bom kimia (Gunawan, 2013). Serangan yang dilakukan oleh rezim Suriah akhirnya menuai kecaman dari dunia internasional, baik itu dari PBB, Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia yang ditindaklanjuti dengan diturunkannya tim investigasi PBB untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia di Suriah.
Lebih lanjut, laporan dari tim investigasi PBB telah memastikan penggunaan senjata kimia gas sarin skala besar dalam serangan di wilayah Ghouta, pinggiran kota Damaskus pada serangan 21 Agustus 2013 lalu (Pujayanti, 2013, p. Menanggapi laporan tersebut, Dewan Keamanan PBB bersama dengan Rusia dan Inggris mengusulkan resolusi dengan opsi serangan militer sesuai dengan Bab VII Piagam PBB.
Namun, Rusia dan China lebih menginginkan jalur diplomasi tanpa kekerasan dalam penyelesaian konflik tersebut yang sesuai dengan Bab VI Piagam PBB. Hal inilah yang kemudian memicu ketegangan antara Rusia dan AS. Di sisi lain, Presiden Assad berjanji menyerahkan seluruh senjata kimia namun AS harus terlebih dahulu mencabut sanksi militer terhadap Suriah (Pujayanti, 2013, p. DK PBB akhirnya membuat resolusi agar Pemerintahan Assad harus menyerahkan daftar lengkap kepemilikan senjata kimia beserta fasilitasnya untuk dihancurkan seluruhnya pada pertengahan 2014. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa laporan dari tim investigasi PBB telah menyatakan adanya penggunaan senjata kimia yang merenggut korban jiwa. Di sisi lain, sikap Presiden Assad untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan senjata kimia juga mengindikasikan bahwa penggunaan senjata tersebut memang dilakukan oleh rezim pemerintahannya.
PBB sendiri telah membuat ketentuan yang berlaku pada untuk melarang pembuatan dan penimbunan senjata kimia, termasuk gas sarin dan menyerukan penghancuran semua stok senjata kimia tertentu pada April 2007. Di sisi lain, dalam pasal 5 ayat 1 poin B statuta Roma dijelaskan bahwa ICC memiliki yuridiksi untuk melakukan pengadilan bagi pihak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, pada pasal 7 dijelaskan bahwa definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah “ any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population” dan ditegaskan pada poin I yang menyatakan “ Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health” (ICC, 1999). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Presiden Assad telah melakukan pelanggaran hukum internasional dengan penggunaan senjata kimia serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa. Namun, hingga saat ini Presiden Assad tidak dibawa ke ICC dan tidak diadili untuk mendapat hukuman. Tidak diadilinya Presiden Assad dan dibawa ke pengadilan internasional tentunya merupakan sebuah anomali bagi penegakkan hukum internasional.
Adanya pengaruh besar dari negara tertentu menjadi salah satu praduga yang dapat diyakini kebenanranya. Selama terjadinya konflik, Rusia terindikasi memberikan bantuan kepada rezim Suriah. Selain itu, Rusia sendiri juga pernah mengirimkan kapal perangnya untuk mencegah masuknya AS ke dalam wilayah Suriah. Di sisi lain pemerintah AS tidak memiliki kepentingan yang cukup kuat untuk harus ikut terlibat dalam konflik tersebut. Pemerintah AS tentu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi seandainya harus mengirimkan pasukannya ke wilayah tersebut. Hal ini berbeda ketika AS melakukan invasi ke Irak untuk menghancurkan rezim Saddam Hussein, serta melanggar kedaulatan Palestina untuk menangkap Osama bin Laden. Perlakuan berbeda yang didapatkan antara Saddam Hussein dan Assad inilah yang menjadi landasan penulis menganggap bahwa hukum internasional belum dapat sepenuhnya ditegakkan dengan baik.
PBB yang seharusnya menjadi wadah dunia internasional dan bersikap netral tidak dapat berbuat banyak karena pengaruh AS cukup kuat didalamnya. Hukum Internasional tentunya dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun yang selama ini terjadi, hukum internasional masih memihak pihak (negara) yang kuat. Satu-satunya solusi idealis yang mungkin adalah PBB harus bersikap netral dan memiliki kekuatan militer sendiri yang melebihi kekuatan negara-negara lainnya. Atau, seluruh negara di dunia bersatu untuk satu tujuan dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga mampu menekan pengaruh negara besar. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana manfaat mengutamakan kepentingan luar negeri disaat kepentingan nasional khususnya bagi negara-negara berkembang masih banyak yang harus diperjuangkan?
Bahkan negara adidaya dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang besar seperti AS sekalipun masih harus mempertimbangkan untung rugi untuk terlibat dalam konflik Suriah. Daftar Pustaka BBC. (2015, Januari 05). Syria: Mapping the conflict. Retrieved Januari 30, 2015, from Gunawan, Y.
(2013, Agustus 26). Kejahatan Kemanusiaan Suriah. Retrieved Januari 30, 2015, from ICC. (1999, Juli 12). Rome Statute of The International Criminal Court. Retrieved Januari 30, 2015, from Khabar South Asia.
(2013, Agustus 29). Kecaman keras atas perang senjata kimia di Suriah. Retrieved Januari 30, 2015, from Pujayanti, A.
(2013, September 16). Isu Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Suriah. Info Singkat Hubungan Internasional, 5-8. Listening this article via podcast Lingstra (beta version). Oleh: Ryan Muhammad, S.H Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA) Jakarta – Indonesia Wakil Direktur Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA). Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris (Cohort 3), Fakultas Strategi Pertahanan, Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia.
Mahasiswa Peminatan Kajian Stratejik Intelijen (Angkatan XIV), Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia. Abstrak Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Eskalasi konflik tersebut juga berdampak meluas hingga berpotensi mengganggu kepentingan nasional negara-negara yang bahkan tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Pemberitaan mengenai isu klaim China atas kepulauan Natuna juga semakin memperkeruh permasalahan yang telah terjadi di kawasan tersebut. Meskipun kebenaran dari pemberitaan tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini, namun isu klaim China atas kepemilikan kepulauan Natuna patut disikapi dan diantisipasi oleh Pemerintah RI karena menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Pengukuran skala ancaman dengan menggunakan metode analisis intelijen “Hank Prunckun” memberikan hasil akhir yang menunjukkan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas kepulauan Natuna tergolong “sedang” bagi Indonesia. Analisis ancaman tersebut dilakukan guna memberikan rujukan akademis bagi Pemerintah RI dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri guna merespon isu tersebut sebagai upaya cegah dini (early warning). • Pendahuluan Konflik laut cina selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini masih belum mencapai titik penyelesaian, serta rawan mengganggu stabilitas kawasan di masa yang akan datang. Sengketa perairan yang menyangkut kedaulatan wilayah perairan negara-negara di wilayah kawasan laut cina selatan ini diawali oleh klaim sepihak negara China yang memperluas wilayah perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Klaim negara China tersebut telah menimbulkan reaksi yang cukup keras dari negara-negara di sekeliling laut cina selatan yang dianggap telah mengancam kedaulatan dan merugikan kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan tersebut.
Sengketa kepemilikan kedaulatan territorial di laut cina selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik laut cina selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah laut cina selatan.
China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas laut cina selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “ Nine-Dashed Line” (Nainggolan, 2013, p. Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah laut cina selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
Negara-negara yang bersengketa dalam konflik laut cina selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militernya masing-masing. Upaya-upaya konfrontatif dalam memperjuangkan klaim atas kepemilikan wilayah laut cina selatan dari masing-masing negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan semakin memperkeruh dan mengganggu stabilitas kawasan, bahkan berpotensi berdampak kepada mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik laut cina selatan, seperti Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di laut cina selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di laut cina selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan laut cina selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan laut cina selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut cina selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara (Nainggolan, 2013, pp. Perkembangan konflik laut cina selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan territorial Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat pemberitaan mengenai klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna yang saat ini masuk ke dalam rincian peta kedaulatan territorial terbaru negara China (NBC Indonesia, 2015). Sebagaimana telah kita ketahui, perairan dan kepulauan Natuna merupakan bagian integral dari kedaulatan territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wilayahnya berada di dalam 12 Mil laut territorial Indonesia yang telah diakui oleh PBB sejak lama dan diperkuat oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Klaim negara China atas perairan dan kepulauan Natuna dianggap tidak berdasar, karena posisi wilayah kepulauan Natuna berada di sekitar lebih 400 Mil dari jarak kepulauan Spratly yang selama ini diklaim oleh China sebagai wilayah teritorialnya (Okezone, 2015).
Namun pemberitaan perihal klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna telah dibantah oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, yang mengutip pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China yang menyatakan bahwa kepemilikan perairan dan kepulauan Natuna adalah mutlak milik Indonesia. Pernyataan Menteri Luar Negeri RI tersebut ditanggapi oleh pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang berpendapat berbeda soal klaim China atas kepulauan Natuna. Ia berpendapat bahwa pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China hanyalah sebatas bahasa diplomatik, peta resmi yang dikeluarkan oleh China justru menyatakan hal yang sebaliknya. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan Juru Bicara Menteri Luar Negeri tidak dapat dikatakan sebagai pernyataan resmi mewakili pemerintah China, karena pernyataan tersebut bukan dinyatakan sendiri oleh Presiden maupun Menteri Luar Negeri China. Akan tetapi, meskipun pemberitaan terkait dengan isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna masih menjadi perdebatan hingga saat ini, namun perlu dilakukan suatu kajian dan analisis mendalam guna memberikan gambaran dan penjelasan mengenai potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas kepulauan Natuna. Tajuk utama dalam pembahasan kajian ini akan berfokus kepada menganalisis ukuran ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menyikapi atau merespon isu klaim China atas sebagian wilayah kedaulatan territorial Indonesia, yaitu perairan dan kepulauan Natuna.
• Kerangka Teori Dalam mengukur seberapa besar ancaman yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi isu klaim China atas kepulauan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, penulis menggunakan teori utama yaitu “threat analysis”, atau biasa disebut dengan “analisis ancaman” guna menjawab pokok permasalahan pada pembahasan kajian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode analisis ancaman yang dikemukakan oleh Hank Prunckun, seorang pakar intelijen asal Australia melalui bukunya yang berjudul “Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis” (2010). Teori yang bermuatan metode analisis ancaman tersebut umumnya digunakan oleh aktor negara untuk mengetahui seberapa besar ancaman yang akan dihadapi oleh suatu negara dalam menghadapi ancaman yang berasal dari aktor non-negara seperti teroris dan pelaku kejahatan lainnya, maupun ancaman yang berasal dari aktor negara seperti ancaman invasi dan bentuk serangan lainnya. Ancaman ialah tekad dan tindakan suatu pihak untuk membahayakan pihak lain. Ancaman dapat berasal dari entitas seperti individu (orang), organisasi/kelompok, maupun negara/bangsa, yang dapat berbentuk serangan fisik maupun non-fisik terhadap pihak yang terancam. Metode analisis ancaman dalam hal ini menggunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu niat/tekad ( intent) dan kapabilitas ( capability). Niat/tekad ( intent) terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu keinginan ( desire) dan harapan ( expectation).
Sedangkan kapabilitas ( capability) terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu sumber daya ( resources) dan pengetahuan ( knowledge) (Prunckun, 2010, pp. Niat/tekad ( intent) dimaknai sebagai tingkat optimisme suatu pihak dalam keberhasilan menyerang sasaran. Kapabilitas ( capability) dimaknai sebagai daya serang atau daya rusak suatu pihak dalam menyerang sasaran. Keinginan ( desire) dimaknai sebagai antusiasme suatu pihak untuk menyebabkan kerusakan pada sasaran dalam mencapai suatu tujuan. Harapan ( expectation) dimaknai sebagai keyakinan yang dimiliki suatu pihak bahwa mereka akan berhasil jika rencana telah dijalankan. Pengetahuan ( knowledge) dimaknai sebagai segala informasi yang dimiliki suatu pihak untuk menggunakan atau membangun perangkat atau melaksanakan proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan terhadap sasaran.
Sumber daya ( resources) dimaknai sebagai sumber daya yang dimiliki suatu pihak termasuk keterampilan dan pengalaman serta bahan yang diperlukan untuk bertindak menjalankan rencana terhadap sasaran (Prunckun, 2010, p. Sehingga jika dirumuskan secara matematis, metode analisis ancaman tersebut akan berbentuk sebagai berikut: Threat = Intent + Capability Threat = (Desire + Expectation) + (Knowledge + Resources) Jadi, berdasarkan rumus diatas, jika jumlah nilai dari setiap elemen semakin besar, maka akan semakin besar pula jumlah nilai ancamannya.
Begitu pun sebaliknya, jika jumlah nilai dari setiap elemen semakin kecil, maka akan semakin kecil pula jumlah nilai ancamannya. Dalam mengukur tingkat ancaman pada metode analisis ancaman seperti ini, umumnya menggunakan skala penilaian angka 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat potensi ancaman yang dihadapi. Oleh: David Putra Setyawan, S.Kom, M.Si(Han) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkar Studi Strategis. Pendahuluan ASEAN merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dalam perkembangannya beberapa negara seperti Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, ikut bergabung didalamnya.
Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh ASEAN beberapa diantaranya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi, kerjasama sosial dan budaya antar anggota, perlindungan stabilitas keamanan di kawasan, aktif berkolaborasi antar negara anggota dalam kerjasama yang saling menguntungkan bagi kepentingan nasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahun dan administrasi/birokrasi, saling menyediakan bantuan fasilitas latihan dan pengembangan di pendidikan, profesionalitas, lingkup teknis dan administratif. Selama proses perkembangannya, hubungan antar negara anggota ASEAN mengalami pasang surut, sebagai contoh adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan latar belakang budaya, sejarah maupun sikap politik masing-masing negara merupakan beberapa faktor penyebab lambatnya perkembangan ASEAN pada awal perkembangannya. Namun, hal tersebut juga dipandang sebagai suatu proses pemahaman dan pengertian untuk menghilangkan rasa saling curiga antar negara anggotanya agar nantinya dapat bekerjasama untuk tujuan yang lebih baik.
Dengan semakin meningkatnya peran ASEAN di kancah global serta untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang jauh lebih makmur, stabil dan berdaya saing tinggi, para pemimpin negara anggota mendeklarasikan Bali Concord II pada KTT ASEAN di Bali, Oktober 2003 untuk bersama-sama membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang ditargetkan pada tahun 2020. Namun pada KTT ke-12 ASEAN di Filipina, para pemimpin negara anggota menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat dibangunnya komunitas ASEAN menjadi tahun 2015 dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembangunan Komunitas ASEAN pada 2015. Komunitas ASEAN sendiri meliputi tiga pilar utama, yaitu Political and Security Community, Economic Community, dan Socio-Cultural Community. Setiap pilar tersebut memiliki landasan / cetak birunya masing-masing yang terintegrasi secara bersama-sama dengan the Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan Phase II (2009-2015) untuk mencapai tujuan bersama khususnya ASEAN Community 2009-2015. Secara garis besar, penjabaran masing-masing pilar adalah sebagai berikut: • Political and Security Community, atau Pilar Komunitas Politik Keamanan bertujuan untuk mencapai perdamaian di kawasan dan tataran internasional dengan beberapa instrumen, yaitu zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral, traktat persahabatan kerjasama Asia Tenggara, Komisi HAM antar pemerintah ASEAN, dan pengelolaan konflik Laut China Selatan.
HASRAT KEINGINAN TITIK TOLAK DARI SEMUA PRESTASI LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI KAYA RAYA KEGAGALAN AKAN MEN GHINGGAPI MEREKA YANG SECARA ACUH TAK ACUH MEMBIARKAN DIRINYA M EMIKIRKAN KEGAGALAN. Ketika Edwin C. Barnes meloncat dan gerbong ke reta barang sesampainya dia di kota Orange, New Jersey, Iebih dan tiga dasawarsa yang silam, sosoknya mungkin Iebih mirip seorang gelandangan, tapi di dalam benaknya merasa menjadi seorang raja! Sambil melangkah menyusuri relmenuju ke kantor Thomas A. Edison, otaknya berpikir keras. Dia mem bayangkan dirinya berdin di hadapan Edison.
Dia bisa mendengar mulutnya bertutur meminta kepada Tn. Edison agar diberi kesempatan untuk menjalankan OBSESI YANG MENGUASAI JIWANYA, sebuah HASRAT YANG BERKOBAR untuk menjadi seorang mitra bisnis dan tokoh penemu besar itu. Hasrat di benak Barnes itu bukanlah sekedar ha apan! Bukan pula sekedar angan-angan! Sesungguhnya itu adalah KEINGINAN yang senantiasa bergejolak dihatinya dan melebihi segalanya. Sebuah keinginan yang tegas dan PAST!
Hasrat itu bukan sesuatu yang barn ketika dia menghampiri Edison, karena dia telah begitu lama menguasai pikirannya. Ketika hasrat itu pertama kali hinggap di benaknya, boleh jadi itu hanyalah sebuah angan-angan, tapi ketika dia berhadapan dengan Edison, jelas dia tak hanya membawa angan-angan. Mohon maaf untuk penerbit, dikarenakan sulitnya untuk mencari buku Think And Grow Rich. Bahkan sudah pesanpun tidak kunjung ada perkembangan, padahal banyak sekali teman-teman di Indo ini yang mencarinya, oleh karena itu dengan blog ini saya memohon izin untuk memposting semua isi dari buku Think And Griw Rich terbitan UFUK Press, terbitan Februari 2007. Semoga dengan postingan saya disini dapat membawa manfaat dan berkah bagi rakyat Indonesia yang membacanya. Mohon maaf apabila postingan think and Grow Rich pada Blog ini terkadang pembaca menemukan banyak sekali kata yang tidak rapi atau salah. Selamat membaca!
Judul Buku: The New Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Pengarang: Napoleon Hill Tebal: v + 453 halaman Penerbit: PT Ufuk Publishing House, 2009—————————————————————————————————– Pertanyaan yang muncul ketika kita memperhatikan atau membaca riwayat hidup orang yang sukses dalam hidup dan kaya secara finansial adalah apa rahasia di balik kesuksesan mereka. Pertanyaan ini juga yang melatarbelakangi Napoleon Hill ketika menulis bukunya Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya). Inilah pertanyaan utama yang mendorong Napoleon Hill menyingkap rahasia kekayaan Andrew Carnegie, sang milioner industri baja kenamaan di Amerika Serikat. Awal kisah penulisan buku ini terbilang sederhana. Tahun 1908, di tengah krisis dan penurunan ekonomi Amerika Serikat, Napoleon Hill menerima pekerjaan menjadi reporter dan penulis pada Bob Taylor’ Magazine.
Sebagai jurnalis, Hill ditugaskan menulis dan menyingkapkan kisah-kisah sukses dan rahasia menjadi kaya dari para pemimpin perusahaan besar di Amerika Serikat. Meskipun merupakan refleksi filsafat kesuksesan atas perjalanan hidup Andrew Carnegie, pemikiran yang terdapat dalam buku ini menjadi fondamen bagi setiap orang yang ingin menjadi kaya. Menarik untuk mengomentari landasan epistemologis buku ini.
Ketika Napoleon Hill mengemukakan keinginannya mewawancarai Carnegie, sang milioner ini menantang dia untuk menyingkap dan menulis prinsip-prinsip dasar yang mampu menjelaskan kunci sukses menjadi kaya dari banyak orang, dan bukan hanya dirinya. Carnegie bahkan mendesak Hill untuk mewawancarai sedikitnya 500 orang—beberapa nama yang terkenal, misalnya Thomas Alfa Edison, Alexander Grahambell, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Woodrwo Wilson, dan sebagainya—untuk mengungkapkan prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih universal tentang rahasia menjadi sukses dan kaya. Menceritakan tantangan yang diajukan Carnegie dalam buku ini, Napoleon Hill sebenarnya menegaskan bahwa prinsip-prinsip atau filsafat kesuksesan yang ada dalam buku ini telah teruji, karena itu pantas menjadi fondamen universal bagi siapa saja yang ingin sukses dan kaya dalam hidupnya. Jelas, secara metodologis, pendekatan yang dipakai Napoleon Hill bersifat induktif. Lalu, apa kunci atau rahasia menjadi kaya?
Bab pertama buku ini mendeskripsikan keberhasilan beberapa tokoh dalam meraih kekayaan finansial dengan maksud untuk menunjukkan rahasia atau kunci di balik kesuksesan mereka. Napoleon Hill menggunakan contoh-contoh ini untuk mengungkapkan prinsip-prinsip dasar atau apa yang disebutnya sebagai rahasia menjadi kaya. Setiap bab buku ini sebenarnya merupakan satu prinsip dasar menjadi kaya dari seluruh prinsip dasar yang ada.
Ada 13 prinsip dasar atau rahasia menjadi kaya, yakni keyakinan pada kemampuan sendiri, autosugesti, pengetahuan khusus, imajinasi, perencanaan terorganisasi, ketegasan, kegigihan, kekuatan master mind, seksualitas, alam pikiran bawah sadar, otak, indra keenam, dan mengatasi hantu rasa takut. Konstruksi pemikiran buku ini tergolong sederhana. Napoleon Hill menemukan semacam kunci meraih kesuksesan dan kekayaan dalam diri orang-orang kaya, pertama-tama bukan karena mereka memiliki ketigabelas prinsip dasar tersebut.
Hill melihat bahwa fondamen itu akan menjadi rapuh jika seseorang tidak memiliki pemikiran atau cita-cita dan keinginan yang kuat untuk menjadi kaya. Bahkan pemikiran (kesadaran) dan keinginan menjadi kaya menjadi kondisi niscaya bagi beroperasinya ketigabelas prinsip mencapai kesuksesan tersebut. Dalam literatur-literatur motivasi, para motivator umumnya berusaha menghidupkan semacam mental magic dalam diri kita. Itulah pikiran atau gagasan menjadi kaya dan keinginan yang teguh untuk menjadi kaya. Pikiran tentang kekayaan membangkitkan gairah dan imajinasi kekayaan, bahkan pada level yang sangat detail, misalnya membayangkan hidup dalam kekayaan finansial, memiliki segala yang dibutuhkan, merealisasikan berbagai mimpi, beramal, dan sebagainya. Imajinasi intelektual semacam inilah yang sebetulnya merangsang keinginan, yang buahnya adalah keputusan atau ketetapan hati menjadi kaya.
Keputusan menjadi kaya inilah yang kemudian mengarahkan seseorang untuk menemukan kunci atau rahasia atau prinsip-prinsip dasar menjadi kaya. Beberapa prinsip atau kunci sukses mungkin kedengaran aneh. Bagaimana menjelaskan autosugesti sebagai salah satu kunci meraih kekayaan (bab 5)?
Karena meraih kesuksesan dan kekayaan berawal dari kesadaran dan keinginan kuat menjadi kaya, maka seseorang, dalam praktik, harus selalu mensugesti diri sebagai orang kaya. Nasihat Napoleon Hill bahkan sangat praktis, dan mungkin lucu bagi sebagian orang: “Lihat dan rasakan uang yang ada di tangan Anda” (h. 115) justeru menjadi bagian dari latihan mental mensugesti diri dan memperkuat kehendak supaya terus berusaha meraih kekayaan.
Tanpa itu keinginan menjadi kaya hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah bisa direalisasikan. Tentu ini berkaitan erat dengan rahasia lainnya seperti pentingnya perencanaan yang matang dan terorganisasi (bab 8), ketegasan (bab 9), dan kegigihan (bab 10). Lalu, apa hubungan antara daya seksualitas dengan dorongan untuk merealisasi dan mencapai kekayaan sebagaimana dideskripsikan Napoleon Hill dalam bab 12 buku ini? Napoleon Hill melihat dengan jeli, bahwa keinginan akan ekspresi seksual menduduki nomor urut teratas dari seluruh rangsangan yang paling leluasa direspon pikiran manusia (hlm 339). Ingat, pikiran yang jernih yang mendorong hasrat atau keinginan dan cita-cita mencapai kekayaan dalam filsafat kesuksesan Napoleon Hill adalah kondisi niscaya bagi realisasi ketigabelas prinsip dasar tersebut. Karena itu, pikiran harus dikelola dengan baik dan benar, antara lain dengan melatih tanggapan terhadap dorongan seks.
Napoleon Hill tidak memandang rendah dorongan seks, tetapi melihat bahwa dorongan tersebut dapat merusak dan menghalangi pencapaian kesuksesan jika dikelola dengan benar. Dorongan seks seharusnya disalurkan secara benar sehingga menjadi daya kreatif, energi atau karisma dalam mencapai kekayaan. “Keinginan akan ekspresi seksual bisa diberikan penyaluran lain yang akan memperkaya ekspresi tubuh dan jiwa, apabila dijinakkan dan diarahkan, daya motivasional ini bisa dimanfaatkan sebagai suatu daya kreatif yang dasyat untuk melahirkan karya sastra, seni, dan untuk tujuan lain, termasuk mengumpulkan kekayaan” (hlm. Lebih dari sebuah teks motivasi, buku ini bisa digunakan sebagai alat pemetaan atau refleksi diri, tidak terbatas dalam upaya meraih kekayaan finansial, tetapi juga dalam pengelolaan uang sehari-hari. Konsep pengenalan diri dengan berbagai kekurangan dan kelebihan, misalnya, mampu mengkategorikan kita sebagai orang yang cukup cermat dalam mengelola keuangan atau seorang pemboros dan penikmat kehidupan. Pengenalan diri semacam ini tentu memiliki relasi yang kuat dengan pentingnya pengendalian diri, memiliki rencana yang teratur, tegas dan gigih dalam mengelola hidup, dan seterusnya.
Dengan kata lain, apa yang dikatakan Napoleon Hill dalam buku ini dapat dibaca sebagai refleksi kritis atas kehidupan kita masing-masing, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan pribadi. Seusai membaca buku ini kita akan menemukan diri berada dalam dua pilihan penting: atau berada pada kelompok orang yang memiliki pemikiran dan keinginan untuk menjadi kaya atau berada dalam kelompok yang menikmati saja hidup ini, tanpa hasrat, tanpa cita-cita atau tujuan.
Berada dalam kelompok pertama akan “memaksa” kita merealisasikan seluruh rahasia yang terungkap dalam buku ini, karena itulah satu-satunya jalan meraih kesuksesan dan kekayaan. Sementara berada dalam kelompok kedua seharusnya segera menyadarkan kita untuk kembali merencanakan hidup secara baik, kecuali kalau kita sudah memilih untuk tidak menjadi sukses dan kaya. Buku ini dipuji jutaan pembaca, terbukti edisi Bahasa Inggrisnya terjual lebih dari 7 juta kopi. Salut kepada Penerbit Ufuk yang berani menerbitkan edisi Bahasa Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya memperkaya literatur motivasi, tetapi menjadi “petunjuk hidup” mencapai kesuksesan dan kekayaan.
